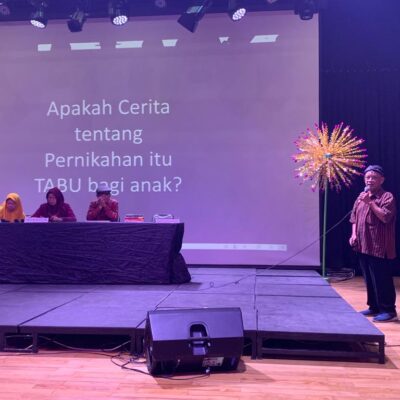Moderasi Beragama di Sekolah
Oleh: Ulfatul Husna
Terminologi Islam Rahmatan lil ‘alamin, demikian popular tidak hanya di kalangan ummat Islam, namun tidak semua artikulatif dengan misi agama tersebut. Meski tidak dipungkiri bahwa semua agama memiliki misi perdamaian, akan tetapi sifat “ego” dalam diri seseorang acapkali muncul terutama ketika mendengar isu tentang agama yang telah dipegang teguh “termarginalkan”, ataupun “ternodai”, maka misi damai tersebut tidak lagi berlaku dalam diri seseorang yang mengklaim dirinya seorang yang paling agamis atau paling benar dalam beragama. Sebab, baginya yang paling penting adalah bagaimana menjaga image dirinya sebagai orang yang beragama dan image agamanya sebagai satu-satunya agama yang mutlak kebenarannya, sehingga esensi agama itu sendiri terabaikan. Sikap ekstrem inilah yang memunculkan sikap intoleran dan radikal. Wajar jika belakangan ini Islam Wasathiyah, atau moderasi beragama menjadi trend di kalangan umat Islam, dan bahkan Menteri Agama memasukkan moderasi beragama dalam program rencana jangka menengah pembangunan bangsa.
Moderasi atau dalam Istilah lain wasathiyah sebenarnya merupakan watak dasar dari agama Islam. Bukan karena ada problem radikalisme, liberalisme, akhirnya agama dimoderasi, akan tetapi justru Islam itu sendiri sudah moderat, dan tidak perlu lagi dimoderasi. Maka sudah menjadi kewajiban bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) (dalam kurikulum 13 disebut Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti) untuk menanamkan moderasi beragama terhadap peserta didiknya. Hal itu sangat penting untuk keberlangsungan NKRI dan melestarikan budaya lokal, sekaligus memantapkan keberagamaan. Untuk menjadi religius, tidak harus merusak kebudayaan/tradisi dan tatanan masyarakat yang ada. Sementara stigma yang terbangun pada kebanyakan masyarakat selama ini bahwa seorang yang religius, yang agamis, yang baik keberagamaannya adalah yang identik dengan budaya Arab. Mulai dari fashion, makanan, bahasa, dan lain sebagianya. Segala macam yang kearab-araban selalu dikaitkan dengan keberagamaan seseorang.
Keberagamaaan yang demikian pun terjadi di lingkungan sekolah. Mulai bahasa sapaan, menggunakan istilah, akhy, ukhty, ‘afwan, syukron. Dalam berbusana pun demikian, berniqob, isbal, berhijab (jilbab panjang lengkap dengan kain penutup punggung telapak tangan. Pun demikian dengan konsumsi makanan yang kearab-araban. Hal demikian seolah menjadi trend anak-anak yang menamakan dirinya remaja muslim yang telah ber-hijrah. Fenomena seperti itu sebenarnya tidak ada salahnya, tapi yang salah adalah ketika dari sikap mereka yang “merasa paling agamis” yang kemudian memunculkan penilaian negatif terhadap temannya yang dinilai “kurang agamis” atau “tidak seperti dirinya” yang ujung-ujungnya memisahkan diri dari kelompok tersebut dan menjadi muslim yang eksklusif. Penilaian terhadap keberagamaan seseorang tidak lagi didasarkan pada agama tetapi lebih pada perspektif diri. Dia selalu beranggapan bahwa paham agamanya yang paling benar, sehingga ia pun tidak mau menerima pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan dia
Terdapat tiga tipologi praktik pembelajaran PAI apabila dikaitkan dengan pendekatan studi Islam normatif menurut Charles J. Adams. Pertama: pendekatan missionaris-tradisionalis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengemban misi mengislamkan non-muslim. Atau dalam lingkup yang lebih kecil adalah mengislamkan pemahaman dan perilaku Islam versi atau sama dengan dirinya atau kelompoknya. Seseorang yang menggunakan pendekatan itu dalam studi Islam, selalu beranggapan bahwa paham agamanya yang paling benar, sehingga ia pun tidak mau menerima pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan dia (eksklusif). Bahkan tidak jarang berita yang dia sampaikan mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok lain.
Kedua: pendekatan apologetic, yaitu pendekatan dengan menggunakan pemahaman agama berbasis romantisme sejarah dan keberhasilan umat Islam secara tendensius. Sehingga memahami ajaran Islam dengan tujuan untuk mempertahankan diri dan bukan tujuan ilmiah. Seorang pendidik yang menggunakan pendekatan ini dalam menyampaikan ajaran Islam, cenderung memaksakan kehendak terhadap peserta didiknya, bagaimana bisa ajarannya itu diserap dan diikuti oleh peserta didik, sebagaimana ia waktu menjadi murid dulu. Sikap apologi itu kemudian dapat memunculkan identitas diri sebagai guru yang berhasil dalam merubah anak didiknya.
Ketiga : Pendekatan irenik yaitu pendekatan dengan upaya memahami pemahaman agama di luar dirinya sebagai upaya simpatik dan agar bisa memahami keyakinan orang lain. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan ini, justru terjebak pada persoalan orang di luar yang tidak sama dengan dirinya, harus menjadi sama dengan keyakinan agama yang dianutnya atau kelompoknya.
Terlepas dari teori tersebut, jika misi agama “rahmatan lil ‘alamin” selalu dipegang, esensi agama tidak akan tercerabut oleh keangkuhan dalam perdebatan masalah khilafiyah yang ada dalam Islam yang sesungguhnya merupakan rahmat bagi ummat Islam itu sendiri. Pun demikian dengan keragaman suku, budaya dan agama yang hakikatnya memang ada, akan tetap terjaga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama yang wasathiyah, yang inklusif, toleran dan rahmatan lil ‘alamin, sangat penting ditanamkan pada peserta didik karena merekalah yang menentukan bagaimana bangsa ini ke depan.
(Penulis adalah guru PAI di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo).