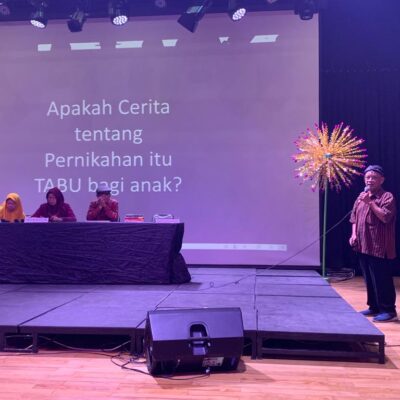Dwijo Sukatmo Sudah Menyatu dengan Gustinya
Oleh HENRI NURCAHYO
Sembilan tahun yang lalu, Dwijo Sukatmo menulis status di fesbuknya: “Hidup ini ibarat antri, nunggu panggilan dari Gusti Allah.” Maka setelah mengalami kondisi kurang sehat selama beberapa tahun terakhir, pelukis kelahiran Surabaya 28 Agustus 1952 ini meninggal dunia dengan tenang, Kamis pagi pukul 07.00 WIB (26/9) di rumah Villa Grand Tomang B 4. NO: 7, Periuk, Tangerang Selatan, Banten, yang dihuninya belakangan ini.
Sebagaimana statusnya satu bulan yang lalu: Manunggaling Kawulo lan Gusti. Kini dia sudah menyatu dengan Gustinya, bersama dengan keluarga besar Akademi Seni Rupa Surabaya (Aksera) yang sudah mendahului: Krishna Mustadjab, M. Daryono, Amang Rahman, M. Roeslan, Gatut Kusumo, Suhardi, Thea Kusumo, AES Su’ud Endi Suseli, Bambang Haryyadjie BS, Sugeng Santoso, Makhfoed, Arifin Hidayat, dan beberapa nama lain termasuk Rudi Isbandi, Tedja Suminar dan O.H. Supono.
Kalangan seniman milenial mungkin kurang akrab dengan namanya, padahal mahasiswa Aksera angkatan tahun 1972 ini adalah salah satu ikon kota Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia, yang layak dibanggakan. Dia sudah memiliki ciri khasnya sendiri dalam melukis. Dwijo adalah pribadi yang mandiri, konsisten, berkepribadian dan tetap teguh dalam pendiriannya di tengah belantara seni rupa di Indonesia selama ini. Dwijo adalah sosok langka di tengah jagad seni rupa yang cenderung makin instan, tergoda oleh teknologi, bahkan sudah menafikan orisinalitas.
Sebagaimana perupa jebolan Aksera lainnya, karya Dwijo “tidak ada yang menyamai” karena memang ada semacam kredo di akademi yang hanya seumur jagung itu, “bahwa sesama pelukis tidak boleh meniru”. Memang semula gayanya cenderung ekspresionis dengan muatan sosial politik, namun sejak penghargaan Karya Utama Biennale XIII Indonesia tahun 1989, Dwijo semakin mantap dan terus bertahan dengan gayanya hingga akhir hayatnya. Tiga perupa lain yang bersama-sama mendapat penghargaan waktu itu adalah Amang Rahman, Boyke Aditya Khrisna dan Ivan Sagito.

Bersama Ana, isterinya, Dwijo mengapit Dahlan Iskan yang membuka pamerannya.
Lukisan-lukisan Dwijo menampilkan figur yang bertumpuk-tumpuk sehingga sulit dikenali dalam sekali pandang saja. Kurator Eddy Soetriyono mencatat, Dwijo sengaja memperbanyak sosok-sosok objeknya. Lalu memecah dan membelah-belahnya dalam potongan-potongan, kemudian menumpang-tindihkannya. Dari situ terciptalah bidang-bidang, yang kemudian dia isi dengan kombinasi warna-warna kuat dan terang serta warna-warna lembut dan gelap, yang kaya nuansa. Maka kanvas-kanvasnya pun hadir seperti dinamika pola yang tanpa akhir. Bentuk berjejer atau overlapping, membaur dalam tata warna yang begitu kaya dan menyala. Warna-warna pesisir yang meriah, kosmopolit, dan modern. Semua itu seperti sebuah dinamika yang mengajak terus bergerak, tak putus-putusnya.
Bentuk objek berjejer dan saling tindih dan membaur samar dalam tata warna yang kaya itu, dianggap berbagai pihak sebagai inovasi yang kreatif dari berbagai pemunculan seniman Indonesia. Rudi Isbandi menulis, dari penampakannya ini lukisannya menjadi riuh atau ramai seakan-akan seperti menyaksikan kelebatan sesuatu yang sedang bergerak cepat, melintas di depan mata.
Dalam kesehariannya memang anak tentara ini terkesan cenderung angkuh, namun sembada dengan capaian prestasinya; Selain penghargaan Biennale XIII, juga Penghargaan Karya Pilihan Ditjen Kebudayaan Koleksi Museum Nasional (1991), Penghargaan Gubernur Seni Jawa Timur (1993), diundang Kerajaan Jordania dan pameran di Museum Amman, dimana karyanya menjadi koleksi Museum Seni Rupa Internasional di Amman. Dialah satu-satunya pelukis Indonesia yang tampil pada Biennale International II Raciborz, Polanda (2000).
Meski demikian, Dwijo tidak segan-segan mengirimkan karya-karyanya dalam Pameran Seni Rupa “Siklus” di Galeri Prabangkara Surabaya (5- 12 Agustus 2019) bersama dengan para pelukis muda dan kurang dikenal, antara lain Yunus Jubair, Ken Adisti, Buggy Budiyanto, Daniel de Quelyu, Luthfi Sakato Nining Zahro dan lainnya.

Dalam arena Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) Mei 2013 Dwijo tampil dalam “Pameran Tunggal Berdua” dengan Makhfoed di Jx International Surabaya. Sebutan ini dimaksudkan bahwa masing-masing pelukis sebetulnya sedang pameran sendiri atau pameran tunggal, namun diselenggarakan dalam waktu dan di tempat yang sama.
Meki lukisannya bercorak modern, mantan pekerja tataletak Koran Memorandum yang berhenti merokok tahun 2002 ini adalah penganut kejawen yang kental, masih menjalankan ritual Jawa membuat apem dan menyebar bunga di perempatan, melempar pisang ke genteng setiap menjelang Puasa. Dia pengagum tokoh Semar yang juga sering dilukisnya. Tokoh Semar pula yang sering diperankannya dalam pertunjukan semasa sekolah lantaran postur tubuhnya yang dianggap gendut menggemaskan. Tak heran dia juga kagum dengan sosok Gatut Kusumo, dosen filsafatnya di Aksera, orangnya gemuk menyenangkan, kayak Semar dan memiliki magnit yang kuat. Belakangan dia tahu Gatut adalah kader PSI (Partai Sosialis Indonesia), pengikut Sutan Sjahrir, hingga Dwijo mengikuti jejak lelaki yang dipanggil Papa oleh kalangan aktivis itu.

Anak kedua dari tujuh bersaudara ini lahir dari pasangan Bapak Soekatmo dengan Ibu Gangsarwati, dibesarkan dalam kedisiplinan keluarga perwira militer TNI-AD, dilahirkan di RS Mardi Santoso Surabaya pada tanggal yang sama dengan ayahnya, 28 Agustus 1924, dan adik perempuan nomor tiga, 28 Agustus 1954. Namun yang mengajari berkesenian justru ayahnya yang tentara itu.
Menikah 24 Agustus 1975 dengan Anna Sudjono, pasangan ini dikaruniai putera-puteri Alfa Eko Ario Sukatmo (1976, Beta Dwi Hapsari Sukatmo (1979) dan Rizki Tri Widodo Sukatmo (1982). Nama Soekatmo, ayahnya, agaknya terus menurun kepada 5 dari 8 cucunya yaitu: Krasnaya Hayati Sukatmoputri, Gangsarwati Sukatmoputri, Tatag Dwijo Sukatmo, Diwasasri Sukatmoputri dan Kirana Trihapsari Sukatmoputri.
Dwijo berulangkali menyatakan terimakasih pada isterinya, Anna, yang nama aslinya adalah Nurul H….., salah satu puteri dari 14 bersaudara dari seorang dosen, Drs. Soedjono Kartosudirdjo. Anna semasa mudanya Juara Pencak Silat, setelah dewasa banyak menulis cerita anak di Jawa Pos dengan sumber cerita dari masa kecilnya sendiri.
Dwijo merasa bersyukur karena nyawanya masih terselamatkan akibat kecelakaan tabrak lari yang menimpanya tahun 2013 yang menyebabkan gegar otak ringan. “Seandainya Tuhan agak ‘serius’ sedikit saja,” tulisnya, nyawanya sudah melayang. Hal yang sama pernah terjadi ketika keluarga Soekatmo, ayahnya, menjadi target ke-15 pembunuhan oleh PKI tahun 1965.
Dwijo yang menyelesaikan pendidikan di Magister Psikologi Untag Surabaya ini pernah menulis; “Kematian adalah ‘hal yang menyenangkan’ karena kita akan bertemu Al Khaliq, Maha Pencipta, di sana ada Ibu dan Bapak serta leluhur yang telah mendahului kita di surga.”
Selamat jalan ya Jo. Semoga tenang di alam keabadian sana. (*)
HENRI NURCAHYO, penulis dan penggerak seni budaya