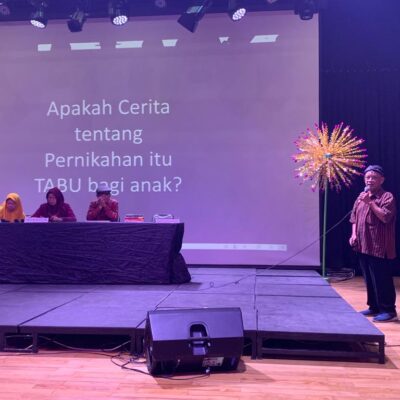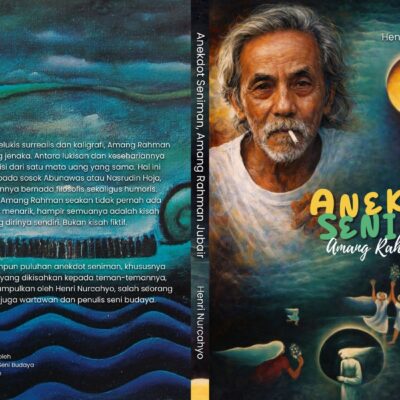Ikan Koi Raksasa di Meja Warisan
Catatan Henri Nurcahyo
HAMPIR dipastikan bahwa salah satu karya yang laris dijadikan objek swafoto dalam ARTSUBS #2 adalah berujud ikan koi raksasa di atas meja yang sedang disantap oleh beberapa orang di sekitarnya. Berada di tengah sebuah ruangan di zona empat, keberadaannya langsung menyita perhatian begitu melihatnya dari jauh. Itu adalah karya patung Entang Wiharso, yang berjudul Under Inheritance. Menggambarkan satu keluarga (suami, istri, anak) dan seorang tamu berkumpul mengelilingi sebuah meja makan.
Secara tersurat, arti kata judul itu sendiri adalah “Di Bawah Warisan” atau “Di Bawah Naungan Warisan.” Dari yang tersaji dari karya ini, tentu yang dimaksud warisan adalah sesuatu yang dilambangkan dengan seekor ikan koi. Mengapa koi? Menurut catatan laman luxati.com, ikan koi tercatat nomor dua paling mahal di dunia setelah Bluefin Tuna atau Tuna Sirip Biru dengan harga mencapai 3,1 juta Dollar atau sekitar Rp 46 miliar. Sedangkan koi termahal pernah mencapai lebih dari 1,8 juta dolar AS (sekitar Rp 28 miliar), jauh mengalahkan ikan arowana yang hanya mencapai Rp 6 – 8 milyar.
Bisa dibayangkan, kalau tubuh ikan koi terpanjang hanya sekitar 1 meter, tetapi yang dipatungkan di atas meja itu lebih dari 2 meter panjangnya. Kalau misalnya ini ikan sungguhan, tentu harganya bisa puluhan milyar rupiah. Lantas, mengapa yang dipajang di atas meja bukan Bluefin Tuna yang paling mahal untuk menyimbolkan warisan? Jawabnya adalah, ikan koi adalah jenis ikan hias yang memang kodratnya jadi tontonan. Jadi secara tersirat harga koi jauh lebih mahal karena bermakna simbolis.
Entang Wiharso (lahir di Tegal, 19 Agustus 1967), lulusan ISI Yogyakarta jurusan seni lukis tahun 1994. Entang dikenal memiliki praktik multidisipliner dan berbicara dengan rasa urgensi melalui saluran apa pun yang tepat untuk kebutuhan mendesaknya, baik itu lukisan, patung, video, instalasi, maupun pertunjukan. Penerima Guggenheim Fellowship tahun 2019 ini hilir-mudik Yogyakarta-Amerika Serikat sejak 1997. Memiliki studio di Indonesia dan Amerika Serikat, kehidupan dan keluarga dekatnya bersifat dwibudaya, dwiras, serta mewarisi beragam warisan agama dan spiritual.
Karyanya kali ini tidak sekadar memotret kebersamaan keluarga. Ia memanggungkan satu komposisi sosial–budaya yang sarat lapisan. Pakaian tradisional yang dikenakan para tokohnya, dan meja bergaya kolonial yang penuh ornamen, serta sebuah ikan koi merah berukuran raksasa di tengah-tengah meja yang tersisa hanya bagian kepala dan ekornya saja. Ini semua adalah simbol-simbol budaya yang sarat makna.
Patung koi karya Entang ini terbuat dari aluminium cor, mulutnya menganga, antara dimangsa atau sedang menunggu giliran menjadi korban. Koi, dalam banyak budaya Asia, adalah simbol harapan, ketabahan, ketekunan, transformasi, dan keberuntungan. Tapi di sini, koi raksasa berwarna merah dengan mulut menganga sedang “dimakan” atau dijadikan objek. Ini bisa dimaknai sebagai warisan yang dikonsumsi. Yaitu budaya yang dulu sakral kini menjadi konsumsi – eksotis, dipertontonkan, atau bahkan “dimanfaatkan.”
Tapi juga bisa bermakna ia adalah korban warisan. Karena koi juga bisa mewakili sesuatu yang diwariskan tetapi kemudian menjadi beban atau bahkan dikorbankan. Ia adalah metafora ambivalen tentang warisan, antara kekuatan yang membanggakan, atau racun yang menyesakkan, tergantung bagaimana kita menempatkannya. Ia bisa menjadi kekuatan pembentuk, tapi juga menjadi beban atau bahkan korban ekspektasi lintas generasi.
Warna abu-abu kehitaman yang menyelimuti seluruh tokoh dan perabotan, hasil dari pelapisan bubuk grafit, seolah menjadi kabut masa lalu yang membekukan gerak. Abu-abu ini sendiri bermakna tidak menawarkan kejelasan moral, tidak menyuruh kita memilih antara baik atau buruk, antara yang luhur atau busuk. Ia justru menyerap dan memantulkan cahaya, seperti warisan itu sendiri: bisa menerangi jalan atau mengaburkan pandangan.
Dengan kata lain bahwa warisan tidak bisa dipandang secara hitam-putih, baik-buruk. Ia hadir sebagai bayangan masa lalu yang membentuk dan mengaburkan masa kini sekaligus. Ini juga memberi kesan kesuraman, nostalgia, atau bahkan keniscayaan. Bahwa warisan selalu menyertai, seperti debu sejarah yang menempel pada tubuh kita.

Empat Wajah di Meja Warisan
Dari empat orang yang mengelilingi meja ini adalah sosok-sosok simbolis yang sarat makna. Misanya, sosok ayah dalam karya ini digambarkan memegang pisau dan mengenakan masker oksigen menutup mulutnya. Dua elemen ini menyimpan makna simbolik yang kuat tentang warisan dan ketegangan antar generasi. Pisau di tangan sang ayah bukan sekadar senjata, melainkan lambang warisan kekuasaan, kekerasan, dan nilai-nilai lama yang tajam. Pisau bisa membentuk, tapi juga melukai. Ia menyiratkan beban sejarah yang diturunkan: patriarki, trauma politik, bahkan kekerasan dalam keluarga atau negara. Sang ayah dihadirkan sebagai pewaris harta dan sekaligus pewaris luka.
Sedangkan masker oksigen menandakan rapuhnya generasi lama yang tak lagi bisa bernapas bebas di dunia hari ini. Ia membutuhkan bantuan untuk tetap hidup, seakan dunia telah terlalu rusak oleh polusi, konflik, atau sistem sosial yang menyempitkan ruang hidup. Masker ini adalah simbol ketergantungan, juga krisis: sang ayah hidup di antara racun, tapi belum mati.
Pisau dan masker oksigen, keduanya membentuk ironi, bahwa warisan yang ditawarkan adalah pisau dan napas pinjaman. Anak-anak generasi berikutnya dihadapkan pada pilihan, antara menerima, menolak, atau mentransformasikannya.

Sosok ibu tampil anggun dalam kebaya, rambut disanggul rapi dengan tusuk konde, sepatu berhak menegaskan wibawanya. Tangan kirinya terbuka, mempersilakan yang lain menikmati hidangan, gestur keramahan yang akrab dalam budaya. Namun tangan kanannya tersembunyi di balik punggung, menyimpan sesuatu yang tak ingin ditunjukkan—rahasia, luka, atau strategi menjaga citra keluarga. Ia menjadi simbol penjaga warisan, memilih bagian yang layak dihidangkan, menutup yang tak pantas terlihat, merangkai wajah tradisi dengan kesempurnaan sekaligus menyimpan bayangannya. Dalam figur ini, Entang memadatkan ketegangan antara tradisi dan kenyataan, antara wajah publik yang sopan dan narasi tersembunyi yang tak semua orang berhak tahu. Warisan, dalam tafsir ini, bukan hanya kemegahan dan kebanggaan, tetapi juga jejak luka yang diam-diam ikut berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di hadapannya, sang anak berkepala gundul duduk rapi dengan kemeja lengan panjang dimasukkan ke celana. Kepalanya disandarkan ke atas meja, mata terbuka menatap sisa tubuh koi. Tatapannya kosong, bukan lapar. Bisa jadi ia malah kekenyangan. Ia adalah potret generasi pewaris yang pasif, hadir tapi tidak terlibat, memandang warisan sebagai sesuatu yang sudah terpotong dan tak utuh, membawa serta kebanggaan sekaligus beban yang tak mereka ciptakan.

Sementara itu, sosok tamu, lelaki berkepala gundul dalam busana formal, tertelungkup separuh tubuhnya di meja. Tangan kirinya terjulur ke arah kerangka ikan, namun sebuah benda tajam menembus telapak tangannya. Tangan kanannya terlipat di atas punggung, gestur yang memunculkan kesan pasrah atau terbelenggu. Ia adalah figur luar yang turut terseret ke dalam pusaran jamuan ini, korban atau saksi dari ketegangan yang mengitari warisan tersebut. Luka di tangannya menjadi metafora bahwa perebutan atau keterlibatan dalam warisan, baik materi, tradisi, maupun ingatan, selalu mengandung risiko untuk melukai.
Melalui figur-figur ini, Entang merangkai narasi lintas generasi yang kompleks. Tradisi yang disajikan dengan wibawa namun menyimpan rahasia; generasi pewaris yang menatapnya dengan jarak; dan pihak luar yang, dalam upaya meraih bagian, justru terluka. Meja makan pun menjelma menjadi panggung pertarungan makna, di mana warisan bukan sekadar pemberian, melainkan medan perundingan, kompromi, dan kadang, pengorbanan.
Dalam komposisi ini, tamu tidak sekadar figur luar yang hadir di jamuan; ia adalah pihak yang terlibat langsung dalam pertarungan makna warisan, menjadi korban atau saksi dari ketegangan yang mengitari meja tersebut. Tangan yang tertembus seolah mengingatkan bahwa setiap warisan, baik materi maupun budaya, menyimpan potensi untuk melukai—terutama mereka yang mencoba meraihnya tanpa memahami seluruh cerita di baliknya.

Hadirnya sosok tamu dalam lingkaran keluarga menambah dimensi tafsir: sebuah representasi dari pandangan luar terhadap budaya Timur. Ia bisa menjadi simbol kolonialisme baru yang datang dengan rasa ingin tahu yang eksotis tapi berujung pada objektifikasi. Tamu itu adalah the outsider’s gaze, sebuah cara budaya luar memandang warisan Timur. Bahwa di era globalisasi dan eksotisme budaya, budaya Asia sering direduksi menjadi stereotip: keserakahan, kelicikan, eksotis. Hadirnya tamu ini bisa dibaca sebagai simbol kolonialisme budaya masa kini, atau menjadi representasi dunia luar yang menikmati tanpa memahami, atau malah mengobjektifikasi.
Tetapi tamu itu juga bisa mewakili bagaimana kita – anak zaman modern – yang kini menjadi “tamu” dalam warisan budaya sendiri. Asing di tanah asal. Bingung di meja nenek moyang.
Bukan Sekadar Pusaka
Secara keseluruhan, karya ini menolak untuk memberikan jawaban yang pasti. Sebaliknya, ia membuka ruang tafsir tentang bagaimana generasi kini menghadapi apa yang diwariskan kepadanya. Bahwa warisan bukan sekadar pusaka, tapi juga pilihan. Bukan hanya tentang menghormati, tapi juga tentang memilah dan menafsir ulang.
Ikan koi—simbol kemakmuran dan ketekunan—di meja ini hanya tersisa kepala dan ekornya. Dagingnya, bagian terbaik yang menyimpan inti kehidupan, telah habis diambil. Warisan yang diterima pun menjadi tidak utuh: hanya menyisakan awal dan akhir, kepala dan ekor, fragmen yang memaksa generasi penerima untuk membayangkan sendiri apa yang terjadi di tengahnya. Bentuk ini juga bisa dibaca sebagai jejak kehilangan, atau tanda eksploitasi—ketika yang diwariskan tinggal bentuk luar dan simbol, sementara substansinya telah dikonsumsi oleh waktu atau pihak-pihak sebelumnya.
Under Inheritance bukan sekadar berada dalam satu garis keturunan budaya, melainkan sebuah kondisi eksistensial, ketika hidup kita—secara sadar atau tidak—dibentuk, dibebani, bahkan diguncang oleh warisan yang datang dari masa lalu. Karya ini menjadi cermin yang mengajak kita menatap wajah warisan kita sendiri. Wajah yang tak hanya indah dan luhur, tetapi juga rumit, kusut, dan sesekali gelap. Ia menggugah kesadaran bahwa mewarisi tidak sama dengan mengulang, dan menghormati tidak selalu berarti membebek.
Warisan adalah ikan koi dalam piring hidup kita. Bisa kita pelihara, bisa kita santap, atau bisa pula kita lepaskan kembali ke sungai masa depan. Pilihan itu ada di tangan kita—namun pilihan apa pun yang diambil, ia akan selalu membawa jejak air dari kolam asalnya, mengingatkan bahwa setiap masa kini adalah percikan dari masa lalu. Dan di sanalah Under Inheritance berbicara: bahwa di balik meja jamuan yang tampak tenang, ada riak-riak sejarah yang terus bergetar di bawah permukaan. (*)