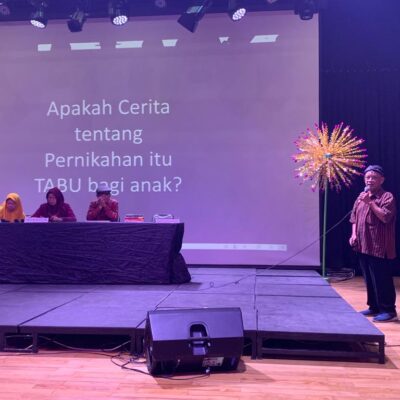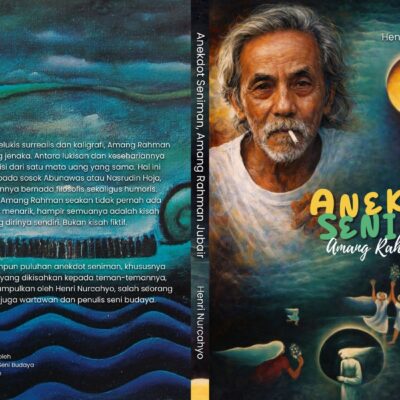Senandung Musik Klasik di Hari Lahir
Catatan Henri Nurcahyo
DI TENGAH hiruk-pikuk kota Surabaya yang meriah menjelang tirakatan peringatan HUT Proklamasi ke-80, sebuah konser musik klasik justru diam-diam berlangsung di barat kota. Jauh dari gemerlap. Sekitar 150-an orang yang hadir. Di ruang kedap suara Amadeo Music Hall itu mereka seakan menemukan oase yang menyejukkan. Denting piano, petikan gitar, gesekan biola, dan alunan cello menggema lirih, seperti doa meditatif yang mengalir di antara ingatan kolektif tentang perjuangan kemerdekaan. Bukan gegap gempita, melainkan keheningan yang mengikat mereka dalam perenungan.
Memang acara ini tak ada hubungannya dengan ulang tahun proklamasi negeri. Hanya kebetulan saja. Tapi ini adalah sebuah momen hari jadi seorang perempuan yang menandai angka 4 terakhir usianya, tepatnya 49 tahun. Namanya Heti Palestina Yunani, seorang jurnalis dan praktisi komunikasi, yang lahir tanggal 15 Agustus 1976 di Lumajang. Ketika orang lain menerima kado saat hari lahirnya, Heti malah berterima kasih dengan mempersembahkan kado berupa konser musik klasik kepada “semua yang memberi saya alasan untuk bertahan,” ujar penggagas dan produser acara konser ini.
“Bagi saya, mengakhiri kepala empat lebih berat daripada menyambut usia 50. Karena itu, saya ingin menandai usia 49 dengan perayaan penuh suara dan rasa. Menghadirkan serta memproduseri sendiri pertunjukan ini adalah cara saya berbagi kebahagiaan sekaligus kado untuk semua orang saat ulang tahun saya,” tuturnya (16/8/25).
Dua tahun lalu, Heti juga merayakan hari jadinya bersama kawan-kawannya dengan menggelar petunjukan ludruk Luntas di kawasan Karang Menjangan Surabaya.
Kali ini kado yang istimewa justru datang dari anak lanangnya, namanya El Vatikan, mahasiswa jurusan musik ISI Yogyakarta, tampil dengan permainan gitarnya yang menawan. Berambut panjang agak berombak, berkaca mata, mengenakan celana batik gombyor feminin karya Embran Nawawi. Ia memainkan gitar seakan tubuhnya membelah diri menjadi dua musisi: jari-jari tangannya mengalirkan irama bass dan melodi sekaligus. Laksana sebuah orkestra mini.
Perancang mode Embran Nawawi-lah yang menjadikan konser musik ini tidak hanya bisa dinikmati secara audio, melainkan menjadi tampilan visual yang cantik. Semua penyaji mengenakan kain batik rancangan Embran, termasuk selembar kain utuh yang dijadikan kerudung oleh Heti Palestina.
M Baqi El Vatikan, nama lengkapnya, lahir di Surabaya pada 21 April 2005, berlatih musik sejak usia 4 tahun, serius belajar musik sejak ia menerima kado ulang tahun yang ke-13. Sejak itu El -panggilannya- mulai belajar mengeksplorasi genre-genre musik. Salah satunya klasik.
Bukan tanpa alasan El memainkan solo gitar karya Antonin Dvorak: Songs My Mother Taught Me. Karya ini mulanya ditulis untuk vokal dan piano pada tahun 1880 berdasarkan sebuah puisi oleh penyair Ceko, Adolf Heyduk. Lagu ini mengisahkan kenangan seseorang atas kidung-kidung ajaran sang ibu yang kini ia nyanyikan untuk anaknya sendiri dengan penuh haru dan rindu.
Songs my mother taught me, In the days long vanished;
Seldom from her eyelids were the teardrops banished.
Now I teach my children, each melodious measure.
Often the tears are flowing, often they flow from my memory’s treasure.
(Lagu-lagu yang diajarkan ibuku, di hari-hari yang telah lama sirna; jarang sekali dari pelupuk matanya air mata benar-benar pergi. Kini kuajarkan pada anak-anakku, tiap alunan yang merdu. Sering air mata kembali mengalir, sering pula ia tumpah dari harta karun ingatanku.)
Bukan hanya kepada ibunya, El juga tampil lagi bersama temannya, Hati Bening (nama yang puitis), membawakan repertoar karya komponis Argentina, Astor Piazzolla, berjudul: Adios, Nonino! Adiós artinya selamat tinggal. Sedangkan Nonino merupakan panggilan sayang untuk “ayah kecil” atau “papá” dalam bahasa gaul Italia-Argentina (ayah Piazzolla berasal dari Italia).
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalimat tadi diartikan “Selamat tinggal, Kakek!” ditulis pada tahun 1959 di New York untuk mengenang Vicente Piazzolla beberapa hari setelah kematiannya. Tema pertama diambil dari lagu “Nonino” yang dibuat lima tahun sebelumnya, didedikasikan kepada orang yang sama. Kemudian melodi baru yang jauh lebih muram dan melankolis menunjukkan rasa duka atas kenangan yang tak akan terulang.
“Selain buat Mama, saya juga sekaligus mempersembahkan buat kakek saya,” ujar El yang masih berusia 4 tahun ketika kakeknya meninggal dunia. Kalangan jurnalis, seniman, dan budayawan Jawa Timur, pasti sangat kenal dengan nama kakek yang dimaksudkannya: Rudolf Matius (RM) Yunani Prawiranegara. Darah seni menurun ke putrinya, Heti Palestina Yunani, dan kini ke cucunya, M Baqi El Vatikan, peraih Gold Price dalam Thailand International Guitar Festival di Chiang Mai, 12-13 Oktober 2024.

Perayaan Suara Rasa
Dalam event yang bernama “Perayaan Suara Rasa” ini El juga tampil bersama teman-temannya yang tergabung dalam komunitas musik “Dua Ketuk.” Nama yang unik inipun mengisyaratkan bunyi yang pelan namun bermakna. Ya, hanya dua ketuk, tidak lebih. Dalam dunia musik, dua ketuk biasanya merujuk pada birama 2/4 atau 2/2 (kadang disebut duple meter). Misalnya, saat kita berjalan kaki—langkah kanan (kuat), langkah kiri (lemah)—itu sebenarnya pola birama dua ketuk.
Seperti perayaan, musik juga tentang berbagi rasa dan kasih. Para pemusik menuturkan isi hatinya melalui melodi yang mengalir ke jiwa pendengar dan tepukan meriah dihadiahkan kembali untuk mengapresiasi mereka yang sudah menyatakan cinta dengan suara. Bersama nada, semua rasa dapat dibunyikan, didengar, dan dirayakan.
Dalam konser kecil ini, musisi-musisi muda berkumpul menampilkan komposisi musik, menyajikan repertoar dari berbagai komponis dan era, dipilih untuk merayakan rasa kasih yang melampaui ruang dan waktu.
Dua Ketuk adalah komunitas dari Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pengelolaan acara pertunjukan seni musik. Mereka berupaya menjadi wadah bagi komponis, pemain dan penikmat musik untuk mengekspresikan, menampilkan dan mengembangkan keterampilan bermusiknya.
Pendiri Dua Ketuk adalah Hati Bening, lahir di Malang pada 16 Mei 2007 dan baru saja lulus dari Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. Pada 2025 ia melanjutkan studi di Prodi Seni Musik ISI Yogyakarta. Meski bertubuh mungil, violis ini tampil percaya diri, bersama teman-temannya: El Vatikan (gitaris), Gabriel Amadeus (pianis, lahir tahun 2005), Bima Sakti Arifin (biola, 2004), Dhani Ahmad (biola alto, 2007), dan Maigty Simatupang (cello, 2007). Semuanya anak-anak berbakat yang masih sangat muda.
Hampir semua karya yang dihadirkan terkesan jadul. Karya Dvorak yang dimainkan El tadi tahun 1880, Amy Beach: Romance tahun 1896, Franz Schubert: Winterreise (1828), David Popper: Hungarian Rhapsody (1893), Robert Schumann: Piano Quartet Op.47; Andante Cantabile (1842). Yang agak baru adalah karya Mario Castelnuovo-Tedesco: Capriccio Diabolico (1935), dan Astor Piazzolla: Adios Anino (1959), serta yang baru saja diciptakan tahun lalu adalah repertoar Lukas Sommer: Third Letter To Father (2024).

Karya yang disebut terakhir itulah yang terdiri dari lima bagian, sehingga total ada 11 repertoar. Sebagai kejutan di akhir pertunjukan dimainkanlah sebuah repertoar dengan judul Happy Birthday Variations untuk piano dan gitar kuintet aransemen oleh Maigty Simatupang. Sebuah persembahan istimewa untuk Mamanya El yang sedang berulangtahun.
Sepertinya, pilihan repertoar yang dihadirkan dalam konser ini mengarah ke suasana gembira dan/atau dihadiahkan untuk sosok perempuan. Misalnya Gabriel Amadeus dan Bima Arifin menampilkan duet membawakan karya Amy Beach: Romance. Pada mulanya karya ini dimainkan oleh sang komponis dan sahabatnya secara perdana di Amerika. Tercatat bahwa para penonton tersihir oleh melodi-melodi lirikal yang saling dilontarkan oleh piano dan biola sehingga ketika lagu selesai, mereka bersorak agar Amy memainkannya sekali lagi. Amy Beach merupakan salah satu komposer terkemuka di Amerika yang merupakan seorang perempuan. Sama seperti Heti yang juga perempuan.
Dalam perhelatan kecil ini lantas disajikan sebuah musik tari tradisional Hungaria karya David Popper bertajuk Hungarian Rhapsody dibawakan oleh Maigty Simatupang dan Gabriel Amadeus. Kehadiran Maigty seakan mewakili pemain aslinya, yaitu Popper yang konon kurang dikenal di telinga pendengar musik klasik. Padahal ia merupakan cellist paling terpandang sepanjang sejarah dengan banyak karya-karya virtuos untuk cello. Salah satunya adalah Hungarian Rhapsody, yaitu musik tari tradisional Hungaria bernama Csárdás dari sudut pandang Yahudi.
Bayangkan pula bahwa dalam perhelatan ini dipertunjukkan sebuah tarian. Tentu saja hanya musiknya, karya Mario Castelnuovo-Tedesco: Capriccio Diabolico melalui petikan solo gitar El Vatikan. Subjudul karya ini adalah “Omaggio a Paganini” karena ditulis sebagai penghormatan kepada virtuos biola legendaris Niccolo Paganini. Ditunjukkan melalui nada-nada energik khas tarian rakyat Italia dan teknik gitar yang rumit, seperti tangga nada cepat, arpeggio, oktaf dan tremolo yang mencerminkan pengaruh Paganini.
Hampir saja lupa, tak tercatat dalam daftar acara, bahwa Gabriel Amadeus belum memperoleh kesempatan tampil solo. Maka anak muda kelahiran Probolinggo ini mempersembahkan solo piano Lyrica Nova no. 1, sebuah nyanyian romantisme paling tulus dari jantung Sergei Bortkiewicz. Para kritikus musik menyebut Lyrica Nova sebagai karya “dreamily lovely”—memikat dan menenangkan jiwa, seperti penghiburan setelah hari yang melelahkan. Musik Bortkiewicz sering kali diumpamakan sebagai “Chopin Slavik yang lebih romantis”, penuh pesona, namun mungkin pernah terabaikan karena dianggap ‘tradisional’ di era yang semakin mencari inovasi.
Bahwasanya konser ini memang terkait dengan seorang perempuan yang sedang menandai hari jadinya, maka bisa jadi salah satu persembahan repertoarnya adalah karya Robert Schumann: Piano Quartet Op.47; Andante Cantabile. Repertoar ini dibawakan secara kuartet oleh Gabriel Amadeus, Hati Bening, Dhani Ahmad, dan Maigty Simatupang. Andante Cantabile merupakan bagian ketiga dari karya ini, sering dianggap sebagai puncak romantisme, dengan salah satu tema terindah pada zamannya. Robert Schumann menuliskannya dengan menjadikan permainan piano Clara—seorang komponis sekaligus pianis brilian yang juga istrinya—sebagai sumber inspirasi.
Meski demikian, konser persembahan hari jadi ini tak melulu tentang suka cita. Hari jadi adalah sebuah penanda, bahwa usia sudah merangkak lebih tua. Masih terbentang perjalananan pengembaraan yang harus dilanjutkan. Maka Dhani Ahmad dan Gabriel Amadeus menghadirkan karya Franz Schubert: Winterreise, No. 15 & 19. Judulnya saja sudah mengisyaratkan hal yang terkait dengan winter (musim dingin). Karena karya ini memang mengisahkan seorang pengembara yang menjelajahi musim dingin.
Pada akhirnya, perjalananan hidup manusia toh berujung pada kematian. Nasihat bijak menyatakan, ingatlah mati dalam hidupmu. Bahwa hidup itu tak abadi. Karya Lukas Sommer: Third Letter To Father, merefleksikan sebuah momen pada pemakaman ayah komponis ketika ia menempatkan barang-barang yang diinginkan turut menemaninya di dalam peti. Beragam variasi tema yang melalui proses permainan ritmis, harmoni dan instrumentasi mengisahkan segala cerita. Sajian ini dibawakan secara kuintet oleh El Vatikan, Bima Arifin, Hati Bening, Dhani Ahmad, dan Maigty Simatupang.

(foto: kabargress)
Musik Tanpa Syair
Berbagai penjelasan tentang sajian musik tersebut di atas memang diperoleh dari catatan tertulis yang sengaja dibuat untuk itu. Penonton memang tak bisa mendapatkannya langsung dari pertunjukan lantaran musik klasik memang tanpa syair. Dan inilah kebiasaan buruk itu, banyak orang yang menikmati musik hanya dari syairnya saja. Maka ketika deretan kaimat itu tidak ada, seolah-olah musik menjadi tanpa makna.
Musik klasik bukan berarti tanpa cerita. Justru, keindahannya terletak pada cara ia berbicara langsung melalui bahasa nada. Untuk menikmatinya, tidak perlu memaksakan diri mencari arti yang pasti; cukup membuka telinga dan hati pada getarannya. Setiap pergerakan melodi bisa dirasakan layaknya perjalanan: ada saat menanjak penuh ketegangan, menurun dengan rasa lega, atau berliku menghadirkan kejutan.
Warna bunyi tiap instrumen menghadirkan tokoh dan suasana: biola yang lirih seakan menangis, petikan gitar yang terasa ringan dan akrab, denting piano yang jernih, kadang lembut dan tegas, lalu cello menambah kedalaman dengan suara hangatnya. Semua instrumen ini seakan berdialog tanpa kata, saling melengkapi hingga tercipta cerita yang bisa dirasakan pendengar.
Kadang musik itu mengalir seperti lanskap dalam imajinasi: sebuah Adagio mungkin mengingatkan pada hujan sore di desa, sementara Allegro membawa ingatan pada riuh pasar pagi. Dan yang tak kalah penting, diam setelah nada terakhir sering menyisakan gema emosi yang lebih dalam daripada musik itu sendiri. Pada akhirnya, musik klasik adalah puisi tanpa kata; ia tidak menuntut kita untuk memahami, melainkan hanya mengajakuntuk merasakan, sehingga ceritanya justru lahir dari dalam diri kita sendiri.
Ada yang bertanya, mengapa membawakan karya-karya komponis lain? Tidak bisakah menyajikan karya sendiri?
Pertanyaan itu wajar muncul. Membawakan karya komponis lain bukan berarti kehilangan jati diri, justru di situlah seorang musisi mengasah kepekaan, memperluas wawasan, dan ikut merawat warisan musik yang lebih besar dari dirinya. Dari karya orang lain, seorang pemain bisa menemukan cara berbicara baru, belajar bahasa musik yang berbeda, dan pada akhirnya menemukan suara khasnya sendiri. Menyajikan karya sendiri memang penting, tapi tanpa dialog dengan tradisi dan jejak para pendahulu, musik pribadi akan terasa sempit. Dan bisa jadi, anak-anak muda yang baru lulus SMA atau masih mahasiswa itu belum pada tahapan mampu menciptakan komposisi musik klasik sendiri. Masih lumayan jauh perjalananannya.
Wajar pula kalau ada yang beranggapan bahwa membawakan karya komponis lain tak ubahnya seperti menyaksikan pertunjukan rekaman belaka. Yang kemudian perlu disimak adalah, bagaimana kualitas pemainnya. Bagaimana caranya menafsirkan partitur: kepekaan terhadap dinamika, tempo, warna bunyi, hingga kemampuan menghadirkan emosi dan konteks karya itu sendiri. Jadi, bukan hanya “memainkan nada yang benar”, tetapi bagaimana ia membuat musik itu hidup dan beresonansi dengan pendengar.
Dalam tradisi klasik, ruang improvisasi memang terbatas, tapi tetap ada: misalnya dalam cara memberi rubato (sedikit kelonggaran tempo), menekankan frase tertentu, memilih pedaling pada piano, atau bahkan menambahkan kadens (semacam improvisasi kecil) di bagian tertentu seperti dalam konserto era Mozart. Jadi, ya, improvisasi dalam batas tertentu dibolehkan—dan sering justru diharapkan—selama tetap menghormati karakter karya dan tidak melenceng jauh dari semangat komponisnya. Tapi, sekali lagi, tentu belum saatnya anak-anak muda potensial ini dipaksa melakukannya. Apa yang sudah mereka capai pada titik ini sungguh sudah luar biasa.
Selamat ulang tahun Heti Palestina Yunani. Anggap saja artikel ini adalah kado sederhana buatmu. (*)