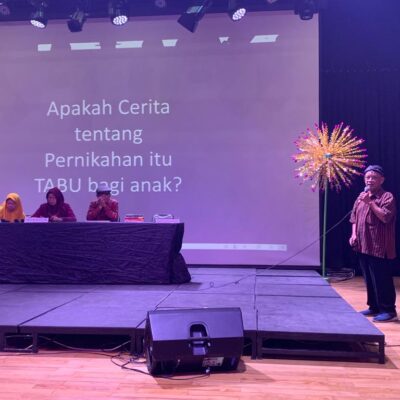Kidung Rajapatni, Bukan Sekadar Dewi Sekartaji
Catatan Henri Nurcahyo

Jum’at malam, 22 November 2014, Sendratari Rajapatni dipentaskan di Candi Brahu. Adakah hubungan kisah Gayatri Rajapatni itu dengan bangunan krematorium Raja-raja Majapahit tersebut? Mungkin itu bukan pertanyaan penting. Yang jelas, postur Candi di Bejijong Trowulan itu menjadi megah ketika Heri Lentho menjadikannya setting pementasan lantaran dikelola dengan tatacahaya yang sesuai dan memperlakukan candi sebagaimana mustinya.
Pementasan yang merupakan rangkaian Festival Trowulan ini memang istimewa. Heri Lentho (47) bukan hanya menjadi sutradara, melainkan menjadi penari utama. Dan inilah pertama kali dia menari (lagi) setelah belasan tahun hanya berada di balik panggung. Tiga penari lainnya adalah penari senior, yaitu Bulantrisna Jelantik (tahun 1965 sudah menjadi mahasiswi Unpad) dan Restu Imansari Kusumaningrum (40), keduanya tinggal di Jakarta serta Cok Istri Ratih Iryani (53) dari Bali. Masih satu lagi yang istimewa, Direktur Musiknya dipegang oleh Rahayu Supanggah (64), komposer yang sudah mendunia.

Malam itu, cuaca sedang berpihak pada acara ini. Langit cerah, penonton leluasa duduk santai di hamparan rumput. Tak perlu kursi, apalagi tenda pelindung hujan. Persis di depan candi, sengaja dibangun panggung rendah, hanya sekitar 50 centimeter, beralaskan kain hitam dan berbatas deretan batu bata agak melengkung sehingga betul-betul menyatu dengan bangunan keseluruhan candi yang juga terbuat dari batu bata. Dan yang mempesona, sistem pengaturan tata cahaya betul-betul menjadikan Candi Brahu sangat anggun, terlihat utuh hingga nampak puncaknya karena disinari dari arah samping.

Begitulah, diam-diam sudah ada sejumlah orang berdiri dalam posisi berbaris dari arah barat. Nyaris tidak ada penonton yang tahu kalau tidak karena banyak juru foto yang kemudian bergerombol mengabadikannya. Padahal para warga Bejijong itu hendak melakukan ritual penghormatan candi sekaligus mengawali pertunjukan ini. Mereka berjalan pelan menuju candi. Dan para juru foto masih memburunya. Suasana sedikit gaduh.
Kemudian muncul barisan orang dari arah sisi selatan candi, membawa peralatan musik, khususnya Singing Bowl, bentuknya seperti mangkuk, biasanya digunakan untuk memulai dan mengakhiri meditasi Buddha Tibetan. Bunyi dengung mangkuk besi itu langsung menyergap suasana hingga jadi khusuk, ditingkahi lantunan mantera-mantera dan bunyi-bunyian khas sebagaimana ritual umat Buddha. Mereka melakukan Pradhaksina, mengitari candi searah jarum jam, seakan mengingatkan kembali bahwa Candi Brahu memang bangunan suci milik umat Buddha.
Mereka yang melakukan Pradhaksina itu ternyata para pemain musik yang menempati posisi di kanan dan kiri panggung. Dua orang, lelaki dan perempuan langsung menuju badan candi di posisi lebih atas. Belakangan diketahui sosok lelaki itu adalah vokalis yang berperan menjadi Mpu Prapanca yang mengisahkan narasi kitab Negara Krtagama. Disusul para penari melakukan ritual yang sama, kemudian pelan-pelan memasuki arena dari arah depan.
Sampai di sini, penonton seakan tersihir oleh suasana mistis lantaran gerak gemulai penari yang mengalun bagai ombak kecil, atau semilir angin yang menghanyutkan. Tarian Srimpi Limo, dimainkan dua perempuan yang menggambarkan dua dari empat Prabu Kertanegara yang menonjol, yaitu Tribhuwana (nama yang sama dengan puteri Gayatri-Raden Wijaya) dan Gayatri, serta seorang penari lelaki yang menggambarkan sosok Kertanegara.
Kisah Gayatri dan Sekartaji
Jalinan kisah yang divisualkan dalam sendratari ini adalah mengenai sosok Gayatri Rajapatni, puteri bungsu Raja Singasari, Kertanegara, permaisuri Kertarajasa Jayawerdana (Raden Wijaya), ibunda Tribuwana Tunggadewi, atau nenenda Rajasanegara (Hayam Wuruk). Earl Drake dalam buku “Gayatri Rajapatni. Perempuan di Bali Kejayaan Majapahit” (2012), menyebut Gayatri adalah sosok yang unik. Berbeda dengan isteri-isteri Wijaya lainnya, Gayatri adalah juga penasehat dan teman diskusi yang cerdas bagi Wijaya dalam mengendalikan negara.
Meski dia tidak pernah secara resmi dinobatkan menjadi seorang Ratu yang memerintah, Gayatri memiliki kekuasaan di belakang layar. Sepeninggal Raden Wijaya, dialah yang menjadi Ibu Suri (yang membimbing) raja Tribhuana Tunggadewi ketika memerintah. Bahkan Gayatri yang mengangkat Gadjah Mada menjadi Mahapatih bagi Hayam Wuruk, cucunya.

Mantan Duta Besar Kanada untuk Indonesia yang menulis buku tersebut juga menceritakan bahwa Gayatri adalah seorang pengagum Cerita Panji. Gayatri mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh Dewi Sekartaji alias Candrakirana. Gayatri juga menyamar ketika bersembunyi dalam lingkungan Keraton Kediri yang baru saja ikut menghancurkan Singasari, kerajaan ayahnya. Hanya saja, tidak sebagaimana Sekartaji yang menyamar menjadi lelaki bernama Panji Semirang, Gayatri tetap menjadi perempuan dengan nama Ratna Sutawan. Sampai akhirnya, Raden Wijayalah yang kemudian hadir sebagai Raden Panji Asmarabangun.

Ketika kutipan atas Earl Drake ini saya unggah di grup FB Sahabat Panji dan Sekartaji, peneliti Panji dan arkeolog Lydia Kieven memberikan catatan kritis: “Sebetulnya belum tentu apakah kehidupan Gayatri bisa disamakan dengan Sekartaji. Belakangan ini memang mitos ini diutarakan oleh Earl Drake dalam bukunya Gayatri (terbitan penerbit Ombak Yogyakarta 2012). Perlu hati-hati jangan mencampurkan fiksi dan fakta historis. Tentu semua yang ada kaitan dengan Panji, adalah campur fiksi dan sejarah.”

Memang, kisah Gayatri yang dihubung-hubungkan dengan Cerita Panji menghadirkan sebuah pertanyaan penting. Kalau betul Gayatri adalah pengagum Cerita Panji, berarti dongeng tersebut sudah eksis sebelum Majapahit berdiri. Bukankah selama ini diyakini bahwa Cerita Panji baru populer pada masa Majapahit meski berkisah mengenai kejayaan zaman Kadiri? Perihal siapa sosok sebenarnya yang disimbolkan sebagai Raden Panji dan Dewi Sekartaji itu saja masih menjadi perdebatan. Meskipun, arus besar mengatakan, bahwa Panji adalah cucu Airlangga, putera Mapanji Garasakan alias Lembu Amiluhur dari Jenggala, sedangkan Sekartaji adalah puteri Raja Kediri, Lembu Amerdadu. Tetapi itu bukan satu-satunya penafsiran.
Beberapa penafsiran tersebut ditulis Agus Aris Munandar dan Ninie Susanti dalam makalahnya “Makna Kisah Panji” di seminar “Cerita Panji sebagai Warisan Dunia” yang diselenggarakan Perpusnas akhir Oktober lalu. Dikatakan, banyak ahli yang telah mengemukakan pendapatnya bahwa Kisah Panji sebenarnya mengacu pada peristiwa sejarah, pendapat-pendapat itu antara lain diajukan oleh C.C. Berg (1927) telah menyatakan bahwa peristiwa sejarah yang diacu oleh Cerita Panji adalah zaman kejayaan Majapahit dalam era Hayam Wuruk. Sementara R.M. Poerbatjaraka (1957 dan 1968) menyorongkan pendapatnya bahwa Kisah Panji sebenarnya menguraikan kehidupan Raja Kadiri Sri Kameswara dengan permaisurinya Kinaratu. Sedangkan W.H. Rassers (1982) mengungkakan bahwa Panji dapat disamakan dengan Ken Angrok dan peristiwa yang berkenaan dengannya; Agus Aris Munandar sendiri (2005) mengemukakan bahwa Kisah Panji mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan 4 orang tokoh penguasa Majapahit sejak awal berdirinya hingga kejayaannya, yaitu Krtarajasa Jayawarddhana, Jayanegara, Ratu Tribhuwanatunggadewi dan Rajasanegara (Hayam Wuruk).
Bukan Sekadar Sekartaji
Jadi, siapakah sesungguhnya Panji dan Dewi Sekartaji? Sebagai seorang kreator, Heri Lentho nampaknya tidak mau dipusingkan dengan perdebatan ahli sejarah tersebut. Seorang Heri Lentho adalah pengagum Gayatri, pengagum Sekartaji, dan pengagum Cerita Panji. Maka berdasarkan buku Earl Drake tersebut di atas, Heri Lentho mengangkat cerita Gayatri dalam sendratari “Surya Majapahit” pada pembukaan acara Temu Karya Taman Budaya Indonesia,11 Juli 2012 di Amphitheater Taman Candra Wilwatikta Pandaan.
Cerita yang sama, judul yang sama, dengan penampilan yang sudah direvisi, disajikan kembali di tempat yang sama dalam acara Festival Majapahit 11-13 September 2013. Menurut pengakuan Lentho, sebenarnya dia ingin menonjolkan sosok Gayatri sebagai judul sendratari itu, namun dia harus kompromi dengan pihak penyelenggara yang nampaknya silau dengan kejayaan Majapahit tanpa memahami sosok di balik layar kejayaan kerajaan besar itu. Gayatri memang bukan sosok populer yang dikagumi, kalah dengan kecemerlangan Raden Wijaya, Hayam Wuruk, bahkan oleh Gadjah Mada.

Baru saat pementasan di Candi Brahu inilah Lentho memiliki kebebasan menentukan judul karyanya sendiri, “Rajapatni”, ketika berkolaborasi dengan Restu Imansari dan para penari senior tersebut. Semula, bukan dia yang tampil sebagai tokoh utama. Tetapi ternyata penari (yang juga senior) yang semula digadang-gadang berperan menjadi tokoh utama membatalkan diri tanpa ada kesempatan mencari pengganti. Maka Heri Lentho, penulis naskah dan sutradara, mau tak mau harus menggantikan tempat Sulistyo Tirtokusumo, penari yang mantan pejabat di Depdikbud tersebut. Beruntung pementasan ini menggunakan topeng sehingga beda usia yang jauh antara Heri Lentho dan Bulantrisna sebagai pasangan Raden Wijaya – Gayatri tidak terlihat janggal.
Memang tidak mudah mempertemukan keempat penari yang berdomisili di kota berbeda itu, sementara masing-masing sudah punya kesibukan sendiri. Bulantrisna sebagai Gayatri, Cok Ratih sebagai Tribhuwana dan Restu Kusumaningrum menjadi Rajapatni saat muda belia. Sementara satu-satunya penari lelaki, Heri Lentho, harus merangkap peran menjadi Krtanegara, Hayam Wuruk dan Gadjah Mada.
Nampaknya Lentho memang bukan sekadar menampilkan Gayatri sebagaimana simbolisasi Dewi Sekartaji yang dilakukan Earl Drake. Bahwasanya seorang Gayatri memiliki kisah hidup dan perjalanan yang menarik untuk direnungkan. Gayatri tidak semata-mata berbicara mengenai keperempuanan namun menjadi lorong untuk menyibak perjuangan hidup, intrik politik, kasih sayang, sosial dan asmara. Fragmen-fragmen penting kehidupan Gayatri yang turut serta mendirikan Majapahit menjadi rangsangan dan sekaligus pancingan untuk ditransformasikan dalam bentuk bunyi. Bunyi sebagai musik. Sebagaimana kodrat musik yang multitafsir, berpendar menjadi beraneka makna, sehingga perjalanan hidup Gayatri dapat menemukan ruang pemaknaan baru. Pada titik inilah kerja cerdas Rahayu Supanggah sebagai direktur musik layak diapresiasi.
Dari pementasan ini, ada dua visualisasi yang menarik perhatian saya. Pertama ketika Raden Wijaya meminang Gayatri menjadi (salah satu) isterinya. Bermula dari Gayatri yang duduk bersimpuh di tengah penonton berpayung daun jati, Raden Wijaya datang dan membimbingnya. Berjalan perlahan mendaki badan candi, keduanya kemudian menari romantis dan berpose lelaki memangku perempuan. Pose ini mengingatkan relief Panji Asmarabangun memangku Dewi Sekartaji yang terdapat di Candi Penataran. Panel relief inilah yang sepertinya disukai arkeolog Lydia Kieven dengan menceritakannya dalam banyak kesempatan.
Visualisasi yang kedua menjelang akhir pementasan ini, ketika Gayatri merasa tugasnya sudah selesai saat Hayam Wuruk sudah naik tahta didampingi Mahapatih Gadjah Mada. Lagi-lagi adegan ini diawali dengan posisi Gayatri yang berada di luar panggung, duduk dikelilingi sejumlah dayang. Disinilah Ibu Suri Majapahit ini memotong habis rambutnya untuk kemudian mengabdikan diri menjadi Bhiksuni. Gayatri telah bertukar busana jubbah Bhikuni, diantar perlahan menuju bagian atas badan candi, menari gemulai tanda kepasrahan dan melepaskan urusan dunia. Kedua tangannya mengembang sedemikian rupa, sebagaimana diabadikan dalam patung Prajnaparamita yang selama ini dikira patung Kendedes itu. Sinar bulat lampu menyorotinya. Pertunjukan selesai.

Bagian terakhir inilah yang tidak terdapat dalam kisah kasih Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Kalau toh seorang Earl Drake menafsirkan Gayatri sebagai pengagum Sekartaji, biarlah itu berada di wilayah perdebatan tersendiri. Dalam hal ini, bisa jadi Gayatri adalah simbol Sekartaji itu sendiri lantaran legenda Cerita Panji memang bukan fakta sejarah, melainkan kisah gubahan yang mengacu kepada peristiwa sejarah yang benar-benar pernah terjadi di (wilayah yang sekarang disebut) Jawa Timur.
Lantas, apa hubungannya dengan Candi Brahu? Konon candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenasah raja-raja Brawijaya, meskipun hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat, karena bilik candi sekarang sudah kosong. Yang jelas, ini adalah candi Buddha, walaupun tak satupun arca Buddha yang didapati di sana, namun gaya bangunan serta sisa profil alas stupa yang terdapat di sisi tenggara atap candi menguatkan dugaan bahwa Candi Brahu memang merupakan candi Buddha. Diperkirakan candi ini didirikan pada abad 15 M.
Menariknya, pemakaian nama Brahu itu sendiri justru mengambil sebutan dari prasasti tembaga ‘Alasantan’ yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau, tepatnya, 9 September 939 M atas perintah Raja Mpu Sindok dari Kahuripan. Nama Brahu dihubungkan diperkirakan berasal dari kata ‘Wanaru’ atau ‘Warahu’, yaitu nama sebuah bangunan suci.
Di satu sisi, konsep Heri Lentho memperlakukan candi Brahu sebagai bangunan suci itu sudah tepat dan patut diapresiasi. Pertunjukan sendratari ini bukan sekadar memanfaatkan candi sebagai latarbelakang belaka, bukan sebagai panggung, melainkan bagian dari pertunjukan itu sendiri. Sayang sekali, ada yang dilupakan, yaitu bagaimana memperlakukan sejumlah keris yang digunakan sebagai properti. Memang ada keris yang biasa-biasa saja, hanya jenis cenderamata, yang dilempar dan sudah patah ujung warangkanya ketika latihan. Namun ketika pentas, lemparan keris ini malah melesat ke arah penonton, padahal seharusnya masih di panggung dan dipungut Gayatri.
Adegan paling mendebarkan, ketika Gadjah Mada hendak melakukan Sumpah Palapa. Tiba-tiba keris yang dipegang Gadjah Mada tidak dapat dilepaskan dari warangkanya. Keris itu seperti melekat erat dengan warangkanya. Maka terpaksa Gadjah Mada bersumpah hanya dengan menggenggam keris masih dalam sarungnya. Akibat kejadian ini, sangat kentara Heri Lentho (Gadjah Mada) tidak begitu tegar mengucapkan sumpah yang legendaris itu. Suaranya bergetar cemas. Menurut pengakuan Heri Lentho seusai pentas, memang dia tidak memperlakukan keris-keris itu sebagaimana mustinya. Padahal sebagian diantaranya keris tersebut “ada isinya”.

Pertunjukan ini memang belum sempurna. Tetapi sudah mampu memberikan suguhan menarik yang memuaskan dahaga batin bagi mereka yang merindukan kesyahduan peninggalan purbakala. Soeprapto Sutyodarmo dari Padepokan Lemah Putih Solo sudah lama menjelajah banyak candi untuk melakukan ritual kesenian, menyatu dengan aura candi dan alam sekitarnya. Bagi Mbah Prapto, kesenian juga cenderung dipahami hanya antar manusia. Kesenian mulai melupakan interaksinya dengan alam dan Tuhan.
Dan sekarang Heri Lentho memberikan kontribusinya yang berbeda. Dia tetap berkesenian untuk sesama, butuh penonton, namun pada ketika yang sama dia menciptakan suasana agar penonton juga menjadi bagian dari pertunjukannya. Setidaknya, secara psikologis penonton digiring untuk sama-sama berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan pertunjukan itu sendiri. Dan itu bukan hal yang mudah dilakukan. (*)