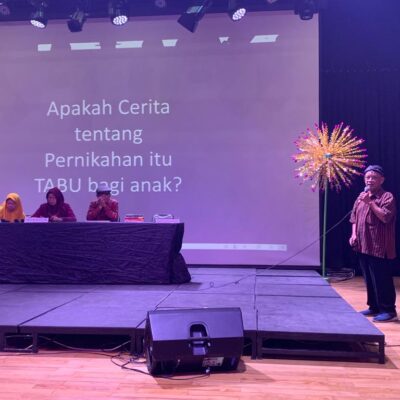Jelajah Budaya Tirtayatra (1) MENGENANG MADE WIANTA
Catatan Henri Nurcahyo
TIRTAYATRA adalah perjalanan ritual ke tempat-tempat suci yang biasanya juga terdapat mata air yang dipercaya sebagai air amerta (air abadi, air kehidupan). Tirta (Tirtha) itu sendiri berarti air suci, air kehidupan, atau tempat suci yang mempunyai air suci. Tirtha dapat juga berarti orang-orang suci, sebab orang-orang suci umumnya berada di tempat-tempat suci yang ada air sucinya. Lantas, bagaimana kalau sekarang ini hendak melakukan Tirtayatra? Maka pilihannya adalah melakukan perjalanan (wisata budaya) mengelilingi Gunung Penanggungan yang diyakini memiliki tempat-tempat suci dan mata air amerta.
Setelah tertunda sekian lama maka Komunitas Seni Budaya BrangWetan melakukan Tirtayatra atau “Jelajah Budaya Lingkar Gunung Penanggungan” (Jum’at, 9 April 2021). Berangkat dari Bungurasih (mobil satu) dan Kampung Seni Pondok Mutiara Sidoarjo (mobil dua dan tiga) rombongan yang hanya terdiri 15 (lima belas) orang itu langsung berkumpul di Candi Jawi, di desa Wates, kecamatan Prigen Pasuruan. Juru Pelihara Candi Jawi, Sulikin, menerangkan panjang lebar perihal Candi yang sangat kaya dengan cerita itu. Sayang sekali waktu terlalu singkat meski sudah berjalan lebih dari satu jam.
Perjalanan berlanjut Candi Belahan di sisi timur gunung Penanggungan, melewati jalan tembus berliku-liku, naik turun menerobos jalanan yang diapit hutan belantara, hingga akhirnya sampai ke posisi belakang candi yang juga dinamakan Sumbertetek ini. Jalanan alternatif ini jauh lebih bagus ketimbang melalui jalur timur yang rusak berlobang-lobang. Lagi-lagi waktu yang terbatas memaksa kami harus harus memburu jadwal Sholat Jum’at sehingga rombongan bergegas turun dan menembus jalur alternatif lagi hingga langsung muncul di Watukosek. Azan baru saja dikumandangkan ketika kami sampai di masjid yang tak jauh dari Pusdiklat Brimob tersebut.
Candi Jedong adalah tujuan berikutnya, terletak di desa Wotanmas Jedong di sisi utara gunung Penanggungan. Konon di desa inilah yang pernah dijadikan Raja Airlangga sebagai ibukota kerajaannya. Tidak banyak yang bisa disaksikan lantaran yang disebut candi Jedong itu sendiri berupa dua buah gapura paduraksa sebagai jalan masuk ke kompleks perumahan para Brahmana dan orang-orang suci. Kawasan perumahan itu sendiri tentu saja sekarang hanya berupa hamparan lahan sekitar seluas lapangan sepakbola.
Tujuan terakhir adalah Candi Jalatunda di sisi barat gunung Penanggungan. Ternyata pengunjung lumayan ramai, padahal bukan Sabtu atau Minggu. Sepertinya candi patirtan ini tidak pernah sepi oleh pengunjung meski dalam masa pandemi sekalipun. Ya sudah, niat mau mandi di kolam akhirnya dibatalkan lantaran selalu penuh dengan orang. Rasanya tak nyaman.
Catatan lebih detail perihal masing-masing lokasi itu nanti akan diuraikan kemudian. Hanya saja, wisata budaya ini mengingatkan saya dengan sosok seniman ternama dari Bali yang bernama Made Wianta. Waktu itu (13 Oktober 2015) atau 6 (enam) tahun yang lalu, saya mengantarkan Wianta dan istrinya menunjungi candi-candi di sekitar Penanggungan. Pertama-tama malah langsung ke Seloliman, karena ada keperluan bertemu dengan Suroso di kantor Lesos untuk tanya-tanya mengenai pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Wianta berkeinginan membuat PLTMH di rumahnya yang dekat dengan danau Kintamani (Batur?). Setelah itu langsung menuju Jolotundo dimana Wianta dengan asyik mengabadikan setiap jengkal batu candi ini dengan kameranya. Bukan hanya candi yang kokoh berdiri di lereng gunung itu tetapi juga batu-batu candi yang masih belum disusun ulang di halaman, maupun yang diamankan dalam sebuah bangunan rumah.
Usai singgah makan siang di PPLH kami lantas melanjutkan perjalanan menembus hutan menuju Candi Jawi. Di tempat ini Made Wianta dan istrinya terlihat sangat menikmati suasana candi di lereng selatan Penanggungan ini. Sebuah foto yang saya ambil dengan kamera saya memerlihatkan mereka berdua sedang bergandengan tangan berjalan menuruni tangga kompleks candi. Sungguh pemandangan yang sangat menyejukkan pasangan harmonis ini.
Perjalanan berikutnya adalah turun ke Pandaan melewati jalur alternatif yang tidak harus melalui Prigen, berlanjut ke utara dan berbelok ke barat melalui jalanan yang biasa dilewati truk-truk pengangkut sirtu. Sepanjang perjalanan terlihat jelas gunung Penanggungan berada di sisi kiri. Waktu itu Mas Wianta berkomentar, “wah kita ini mengelilingi gunung Penanggungan ya. Mungkin orang dulu sambil naik kuda. Kita sekarang naik kuda Jepang.”
Sampailah kami di Candi Belahan yang terletak di Dusun Belahan Jowo, Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Sebagaimana di Jalatunda, ini juga merupakan candi patirtan. Ada kolam di halaman depannya. Yang menarik, di dinding candi ini nenempel dua buah arca, yaitu Dewi Shri dan Dewi Laksmi, dimana salah satunya mengucurkan air dari payudaranya. Kami berfoto-foto di situ sambil berangkulan.
Lantaran sudah sore, kami langsung kembali ke Surabaya. Kami tidak singgah ke candi Jedong, waktu tidak cukup. Sampai di Surabaya kami sempat makan malam di eks Pujasera Diponegoro. Pada saat itu Mbak Intan Kirana, istri Wianta, menyatakan kepuasannya dalam perjalanan ini. Menurutnya, tempat-tempat yang dikunjungi sangat bagus, makanannya juga enak, perjalanan lancar dan menyenangkan.
Dalam perbincangan sepanjang perjalanan itu Wianta melontarkan gagasan agar saya membuat paket Wisata Tirtayatra. Mengelilingi candi-candi di lereng gunung Penanggungan.
“Bagi orang Bali, Jalatunda itu ibarat Mekkah bagi orang Islam,” ujar Wianta.
Saya terdiam sambil membayangkan kesakralan Jalatunda bagi orang Bali.
“Bikin paket wisata Mas, nanti saya bantu memasarkan di Bali,” sambung Wianta lagi.
Ini sebuah gagasan yang cemerlang. Paket itu bisa dibuat dengan rute mengikuti arah sinar matahari. Mulai dari Candi di selatan, bergeser ke candi Belahan di sisi timur, melambung ke sisi utara menuju candi Jedong dan berakhir di Jalatunda ketika matahari sudah bersinar dari arah barat. Arah perjalanan yang berlawanan dengan arah jarum jam ini namanya Prasawiya dalam Hindu dan Buddha atau sama dengan ritual Tawaf dalam Islam.
Ritual tawaf sebetulnya bukan hanya milik Islam, tradisi ini sudah sangat tua dan dijalani oleh hampir semua agama. Masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi tawaf keliling benteng setiap malam Satu Sura. Prasawiya dilakukan untuk membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, sementara pradaksina ditujukan untuk membentuk moralitas. Nah, bikin paket tawaf wisata keliling gunung Penanggungan, mengapa tidak?
Setelah itu saya membuat artikel untuk brosur paket tersebut. Namun entah mengapa gagasan yang sudah saya rancang dengan rapi itu tidak pernah terlaksanakan hingga bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya, saya mendengar Wianta jatuh sakit akibat kecelakaan. Hal ini berlangsung hingga setahun lebih. Niat hati hendak menjenguknya ke Bali tidak pernah kesampaian. Maka berita perihal lelaki yang sebelumnya tidak pernah sakit itu sungguh sangat mengguncang: “Made Wianta meninggal dunia pada tanggal 13 November 2020.”
Made Wianta telah pergi untuk selama-lamanya pada usia 71 tahun. Belakangan ini saya terkenang kembali dengan perjalanan keliling gunung Penanggungan itu. Saya terkenang dengan keramahannya menyambut saya dan Shakti, anak saya, ketika menginap di rumahnya beberapa hari. Kami diantarkan dengan mobil keliling-keliling tempat kesenian, mulai dari yang kelas pantai Kuta hingga yang eksklusif di Ubud, termasuk galeri milik seniman dari Italia (?) yang mengisahkan usahanya sejak masih ngamen melukis hingga memiliki galeri sendiri.
Mas Wianta dan Mbak Intan Kirana, istrinya, adalah pasangan suami istri yang serasi. Mbak Intan yang cucu pahlawan nasional Ki Hadjar Dewantara itu adalah arsitek lansekap yang memiliki usaha dalam bidang tanaman. Mereka juga akrab dengan keluarga kami. Setiap kali mereka berkunjung ke Surabaya juga selalu bertemu saya dan istri. Bahkan ketika mereka tidak memiliki waktu cukup untuk bertemu, Mas Wianta dan Mbak Intan mengundang saya dan istri sekadar makan bersama di resto bandara Juanda sambil menunggu keberangkatan pesawat.
Ah…. Mas Made, baru sekarang ini saya sempat mewujudkan paket Tirtayatra itu, setelah 6 (enam) tahun kita pernah bicara serius. Maafkan saya ya. Semoga Anda tenang di alam keabadian. Saya akan terus mengenangmu selama perjalanan keliling gunung Penanggungan. Membayangkan kita berdua sama-sama menunggang kuda sambil bertukar gelak tawa.
Buat Mbak Intan, salam kangen saya dan keluarga, hingga sekarang kita belum bisa bertemu lagi setelah sekian tahun lamanya. Semoga njenengan sehat-sehat saja yaa. Amiin…..
(Bersambung)