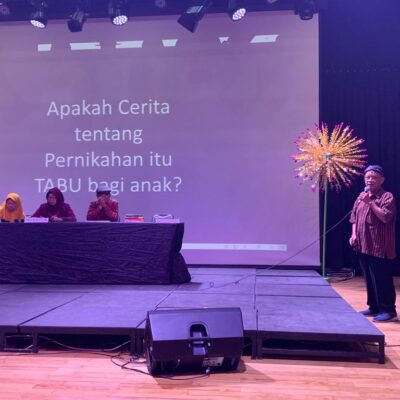Wiruncana Murca, Wayang Topeng Tanpa Topeng
Catatan Henri Nurcahyo
Komunitas Tomboati Jombang menggelar pementasan Wayang Topeng dengan lakon “Wiruncana Murca” di aula SMKN 3 Jombang yang dimulai Kamis malam (21/12) hingga Sabtu (23/12) dalam 5 (lima) kali pementasan. Pertunjukan ini merupakan reinterpretasi dari kesenian tradisi khas Jombang Wayang Topeng Jatiduwur namun tanpa menggunakan topeng seperti aslinya, diganti dengan make up seperti topeng.
Wiruncana Murca adalah lakon lama yang biasa dibawakan oleh Wayang Topeng Jatiduwur meski bukan lakon yang populer. Lakon yang lainnya adalah Patah Kudanarawangsa, Panji Wasengsari dan Jumenengan Panji yang mengadopsi dari cerita Wayang Krucil. Makna kata “murca” itu sendiri dari bahasa Sansekerta adalah “hilang, musnah”. Sedangkan Wiruncana adalah nama tokoh utama dalam lakon ini.

Alkisah Prabu Klana Jaka (diperankan Mustaqim) dari kerajaan Rancang Kencana kehilangan salah satu puteranya yaitu Panji Kudanarawangsa (Qowiyudin Shofi). Karena sedang ada serangan pagebluk (wabah penyakit menular) maka diperintahkanlah Patih Sundul Mega (Firman Hadi Fanani) dan Tumenggung Pancat Nyawa (Tripilu) untuk mencarinya sekaligus mengkuti sayembara di kerajaan Ngrawan yang akan memperebutkan Dewi Kumudaningrat (Disla Apriliani Putri). “Berangkatlah dan menangkan sayembara itu untuk Raden Panji Kudanarawangsa,” pesan Raja.
Berangkatlah keduanya menjalankan tugas disertai segenap pasukan. Kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pengembara beserta dua orang temannya, Bancak (Maula Rofi) dan Doyok (Sulikhul Amin). Terjadilah peperangan yang berakhir dengan kemenangan pasukan kerajaan karena sang lawan lebih suka melarikan diri.
Sang pengembara lantas mendatangi seorang Pandito (Izzudinil Qowim) di sebuah padepokan. Pandito yang sakti ini tahu persis siapa sebenarnya jatidiri si pengelana, namun diminta merahasiakannya. Pandito lantas memberikan sebuah pusaka berupa busur panah yang akan dipergunakan mengikuti sayembara di kerajaan Ngrawan untuk memperebutkan Dewi Kumudaningrat.

Dalam sayembara itu Patih Sundul Mega dan Tumenggung Pancat Nyawa tidak berhasil memanah sebuah sasaran. Kemudian datanglah seorang pemuda yang mengaku Wiruncana dari sebuah desa untuk mengikuti sayembara. Raja Ngrawan Raden Carang Aspo (Ali Rizqoh) meremehkannya dan mengancam akan memenggal leher pemuda itu manakala gagal memanah. Tetapi kemudian semua dikagetkan karena Wiruncana berhasil memenangkan sayembara. “Siapa kamu sebenarnya anak muda?” tanya Raden Carang Aspo.
Maka dibukalah penyamarannya, bahwa pemuda desa itu sesungguhnya adalah Raden Panji Kudanarawangsa. Semuanya lantas menghormat. Raden Carang Aspo kaget karena ternyata Wiruncana adalah kakaknya. Selesai.
Begitulah cerita ringkasnya. Tidak perlu ditunjukkan pesta pernikahan Dewi Kumudaningrat dengan Raden Panji sebagaimana janji sebagai hadiah bagi pemenang sayembara. (Apalagi malam pertama, hush). Juga tidak perlu lagi diceritakan apakah kemudian pagebluk di kerajaan Rancang Kencana dapat teratasi. Anggap saja sudah berhasil.
Pertunjukan ini berjalan linier dan mudah diikuti karena ada peran dalang (Nanda Sukmana) yang menyampaikan narasi. Di sinilah perbedaan dengan pertunjukan asli Wayang Topeng Jatiduwur dimana dalang juga membawakan semua dialog pemain. Dalam pertunjukan ini para pemain dapat berdialog sendiri karena memang tidak terhalang oleh topeng seperti aslinya.
Sebagaimana sebuah pertunjukan, tentu saja ada bagian adegan yang menghibur yaitu ketika dihadirkan Bancak dan Doyok menemani junjungannya dalam pengembaraan di tengah hutan. Ada sejumlah dialog yang setidaknya cukup menghibur dan membuat tertawa sebagian penonton meski tidak seberapa lucu. Sutradara (Fandi Ahmad) kurang berani memasuki situasi masa kini yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang seharusnya dapat menjadi bahan kritik sosial dalam bungkus guyonan. Hanya disebut satu kata “Pilkada” namun tidak dimanfaatan untuk bahan guyon parikena. Pada babak inilah sebetulnya juga dapat dimanfaatkan menarik simpati penonton yang sebagian besar mahasiswa dan pelajar itu dengan menghadirkan persoalan-persoalan seputar dunia pendidikan.
Tapi sudahlah, mungkin sutradara tidak berminat untuk menghadirkan kritik sosial dalam pertunjukannya. Toh dalam bentuk aslinya memang juga seperti itu. Tetapi sebetulnya di sinilah peluang untuk menunjukkan kreativitas sebuah pementasan teater (modern) dan bukan sekadar replikasi pertunjukan seni tradisi. Entahlah, apakah sutradara tidak memikirkannya sampai di situ atau menyerahkan sepenuhnya kepada improvisasi Bancak dan Doyok.

Catatan kedua, pementasan ini dikonsep dengan panggung seperti teater arena, dimana penonton duduk lebih tinggi di trap-trap. Pilihan setting ini memang menghadirkan suasana yang akrab antara pemain dan penonton di bagian depan yang nyaris menyatu dengan pemain sebagaimana teater rakyat. Berbeda dengan konsep panggung proscenium yang menjauh dari penonton. Hanya sayangnya kedekatan ini tidak dimanfaatkan dengan menciptakan suasana interaktif antara pemain dan penonton. Mengapa tidak ada pancingan dialog nakal yang merangsang penonton nyeletuk misalnya. Kalau perlu, menggoda penonton dengan langsung menyebut namanya sekalian.
Berikutnya, ngapain sih petugas panggung (stage crew) ketika membawa properti harus juga berjalan dibuat-buat seperti menari? Apalagi pilihan arah berjalannya malah melintasi panggung, bukan memilih yang paling dekat untuk masuk, sehingga mengganggu pemandangan. Tapi kalau buat lucu-lucuan gak papalah, toh ada juga penonton yang tertawa menyaksikan cara mereka berjalan. Dalam brosur peran mereka disebut “orang hitam”.
Satu hal lagi, setting panggung nampaknya terlalu meriah dengan banyak elemen dekorasi sehingga malah mengganggu fokus pada pemain. Gambar-gambar dengan motif batik berwarna pink dan putih seperti desain batik itu rasa-rasanya kok malah tidak memperindah. Mungkin ada baiknya dibuat minimalis saja.
Last but not lease, apapun yang dipentaskan ini memang wilayah otoritas sutradara. Sah-sah saja menghadirkan model pertunjukan seperti itu untuk sebuah reinterpretasi kesenian tradisi, khususnya lakon Panji. Bagi Komunitas Tomboati, produksi ke 40 (empat puluh) ini adalah sebuah catatan prestasi tersendiri. Setidaknya komunitas ini sudah berusaha memopulerkan kesenian tradisi Wayang Topeng Jatiduwur ke tengah-tengah penonton muda, orang-orang kota, bahwa di Jombang ada kesenian tradisi yang layak dibanggakan. Bahwa di Jombang bukan hanya ada Besutan saja. Nah dengan adanya pementasan ini dapat menjadi promosi bagi kesenian aslinya untuk mengundang penonton yang ingin menyaksikan bagaimana kalau para pemain mengenakan topeng yang asli.
Tinggal sekarang, apakah grup wayang topeng Jatiduwur itu sendiri siap menghadapi perubahan dengan tumbuhnya minat anak-anak muda sebagai akibat dari “penteateran” seni tradisi tersebut. Apakah ada pementasan berkala di Jatiduwur sendiri misalnya, sehingga masyarakat dapat menyaksikan di habitat aslinya. Ataukah diperlukan pula pentas wayang topeng Jatiduwur yang asli di tempat lain yang ajeg sebagaimana pernah dipentaskan di Kediri dalam Festival Panji Nasional bulan Juli yang lalu.

Bagaimanapun sebuah gelombang perubahan digerakkan, maka akan terjadi berbagai konsekuensi yang mau tidak mau harus diterima dengan segala plus minusnya. Termasuk juga, pihak pemerintah daerah harus siap mengantisipasi perubahan ini. Bahwasanya wayang topeng Jatiduwur bukan hanya kesenian tradisi milik warga desa setempat, bukan lagi hanya diposisikan sebagai objek penelitian akademis belaka sebagaimana yang telah terjadi.
Ini lho Wayang Topeng Jatiduwur, yang berbeda dengan Wayang Topeng Malangan dari Malang atau Topeng Dhalang dari Madura. Kesenian di Jombang itu bukan hanya ludruk Besutan dan seni Islami saja. Kalau Sandhur Manduro saja, juga dari Jombang, sudah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional tahun ini, bukan tidak mungkin Wayang Topeng Jatiduwur juga bisa diajukan mendapatkannya. Dengan catatan, apalah artinya sebuah penetapan manakala hanya berhenti sebatas sertifikat? Bahwasanya tindakan nyata jauh lebih diperlukan. Begitulah. (*)