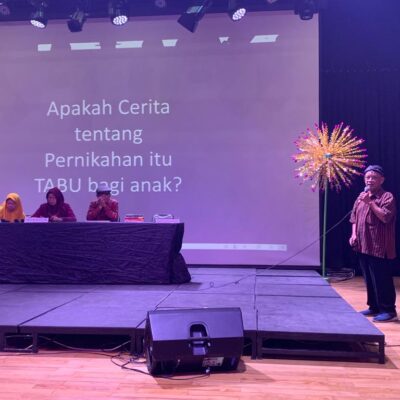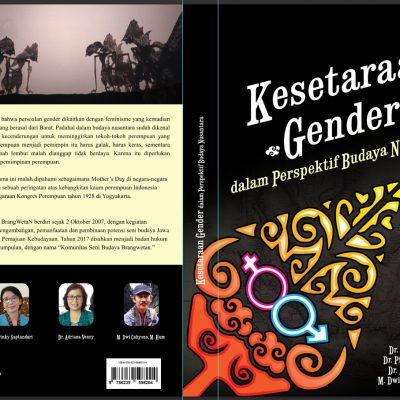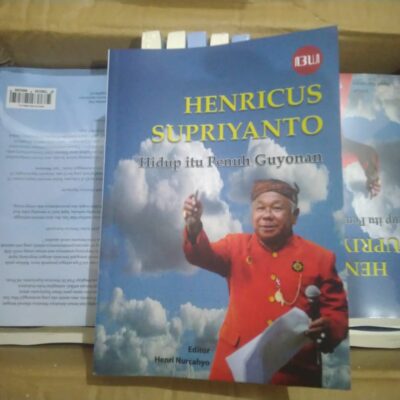Ekspresi Budaya di Tengah Pandemi
Catatan Henri Nurcahyo

Gara-gara pandemi Covid-19 maka semua orang dipaksa berada di rumah saja. Bekerja dari rumah, beribadah di rumah, sekolah hanya dari rumah. Semua aktivitas pertemuan yang melibatkan banyak orang juga harus dilakukan dari rumah saja melalui bantuan teknologi internet. Wacana kesehatan dan ekonomi lantas dipertentangkan. Seolah-olah kalau masyarakat memilih tetap sehat maka harus rela ekonominya terganggu. Pilih mana: Lapar atau mati? Duuh.
Salah satu sektor yang terdampak adalah kesenian. Tidak ada lagi pertunjukan tari, teater, musik, pergelaran wayang kulit, ludruk, ketoprak dan semua seni pertunjukan. Juga pameran seni rupa, baca puisi, pawai budaya, dan termasuk juga ritual upacara adat. Tidak ada lagi diskusi budaya, seminar, bahkan hanya sekadar latihan menari saja dilarang. Semuanya tidak diperbolehkan. Kalau masih bersikeras, lakukan dari rumah saja, manfaatkan teknologi zoom dan semacamnya. Apakah hal itu menjawab persoalan? Tentu saja tidak.
Pemerintah menyadari bahwa larangan tersebut harus disertai dengan kebijakan digelontorkannya bantuan ekonomi kepada masyarakat terdampak. Tidak terkecuali untuk seniman. Ini juga tidak menjawab persoalan. Disamping jumlahnya yang sangat minim, juga tidak menjangkau semua seniman yang membutuhkan. Bahkan, kalau toh misalnya jumlahnya mencukupi, apakah hal ini menyelesaikan persoalan? Sekali lagi, jawabannya adalah “tidak!!!”
Ada konsekuensi psikologis yang barangkali tidak diperhitungkan, bahwa pemerintah secara tidak sadar menjadikan masyarakat (termasuk seniman) bermental pengemis. Masyarakat dipaksa tetap berada di rumah saja, jangan kemana-mana, tunggu saja bantuan dari pemerintah. Bagi seniman sebagai pekerja kreatif, sesungguhnya ini merupakan sebuah penghinaan. Seniman bukan (hanya) butuh makan dari hasil karya seninya melainkan ada kebutuhan rohani yang dapat tercukupi manakala ekspresi keseniannya tersalurkan.
Dalam prakteknya, memang banyak seniman yang kehilangan pendapatan karena pertunjukan kesenian dilarang. Tetapi selama ini, ketika masih banyak pertunjukan digelar sebelum pandemi, apakah semua seniman memang sudah bisa hidup layak dari keseniannya? Memang banyak seniman yang sudah bisa mendapatkan penghasilan melimpah dari karya seninya, tetapi yang hidup miskin dan berpenghasilan minim, jauh lebih banyak lagi.

Pergelaran wayang kulit dengan dalang kondang misalnya, butuh puluhan juta rupiah untuk dapat menggelarnya. Sang dalang bisa memperoleh honor jutaan rupiah, yang angkanya akan semakin menurun diterima seniman pendukungnya sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Tetapi berapa rupiah yang diterima sebagai honor untuk penabuh gong misalnya? Bisa sampai ratusan ribu? Itupun besaran honor dalam sekali pentas. Lantas, ada berapa kali pergelaran dalam sebulan? Bagaimana dengan dalang-dalang tidak terkenal yang hanya menerima permintaan pergelaran satu bulan sekali? Bahkan kurang dari itu?
Seorang pimpinan kelompok ludruk memberikan data yang saya minta, bahwa honor tertinggi bagi pemain ludruk adalah pemeran pelawak sebesar Rp 500 ribu, sedangkan yang terendah adalah pemain pemula sebesar Rp 150 ribu. Sedangkan penabuh gamelan (niyaga) berada dalam kisaran angka Rp 175 ribu sampai Rp 400 ribu. Ini data dari kelompok ludruk ternama yang laris tanggapan. Dalam masa normal sebelum pandemi bisa pentas sekitar 20 kali dalam sebulan. Bahkan lebih. Tapi bagaimana dengan kelompok ludruk yang hanya 1-2 kali mendapat tanggapan dalam sebulan? Ketika sekarang ini pandemi melanda, maka sama sekali tidak ada pemasukan apa-apa lantaran memang tidak ada yang menanggap lantaran terkena larangan mengumpulkan massa.

Bagi seniman, kebutuhan rohani sesungguhnya jauh lebih penting ketimbang kebutuhan ekonomi. Dan itu sudah terjadi sebelum pandemi melanda negeri ini. Banyak seniman yang lebih mengedepankan kebutuhan ekspresi seni ketimbang memanjakan urusan pribadi. Karena ekspresi seni budaya bisa mengalahkan segala-galanya. Laku atau tidak laku, pelukis harus tetap pelukis meski tanpa pameran. Ada atau tidak ada permintaan pentas, penari harus tetap menari, seniman teater tetap berteater, penyanyi tetap menyanyi, musisi harus tetap memainkan instrumennya, penyair harus tetap menulis dan baca puisi. Termasuk juga, ritual upacara adat harus tetap dilaksanakan lantaran hal itu merupakan ekspresi budaya yang tidak dapat dibendung dengan alasan apapun. Ritual budaya adalah cara manusia menghormati alam semesta. Jangan sekali-sekali melarangnya. Bisa kualat !!!

Sudah berapa lama pandemi ini melanda? Masih berapa lama lagi masyarakat harus berdiam di rumah saja? Berkarya dari rumah, pertemuan digelar dari rumah saja? Kerumunan manusia masih menjadi larangan utama, kecuali mungkin untuk keperluan Pilkada. Sungguh ini realita yang menyakitkan.
Seniman harus tetap berkarya. Jangan sekali-sekali melarangnya. Soal larangan berkerumun yang dikhawatirkan menjadi sarana penyebaran virus, itu bisa disiasati. Seniman toh insan kreatif yang tidak bodoh. Ekspresi budaya harus tetap terjaga. Bahkan kondisi pandemi ini sekaligus juga menjadi introspeksi kalangan seniman sendiri. Bahwa seniman musti mengedepankan aspek kualitas bukan semata-mata soal kuantitas. Pergelaran dengan penonton melimpah di lapangan terbuka memang harus dihindari, tetapi pergelaran dengan jumlah seniman terbatas di lingkungan yang juga terbatas, masih dapat dilakukan.
Pentas secara online (dalam jaringan, daring) yang selama ini dilakukan sebagai alternatif memang sudah terjadi. Penonton masih dapat menikmati pertunjukan melalui jaringan internet di masing-masing komputer atau telepon selulernya. Tetapi, sekali lagi, hal itu bukan merupakan jawaban yang memuaskan. Ada ekosistem seni budaya yang hilang. Ada ekspresi budaya yang tidak tersalurkan bagi penonton sekalipun. Hakekat pergelaran kesenian bukan semata-mata mentransfer sebuah tontonan agar dapat disaksikan masyarakat, melainkan ada nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Analog dengan model pembelajaran selama pandemi ini, tidak dapat semata-mata digantikan dengan pembelajaran secara daring. Makna pendidikan itu bukan sesempit pengajaran, yang hanya transfer of knowledge. Pendidikan itu bukan kursus ketrampilan. Begitu juga pertunjukan kesenian bukan semata-mata penyampaian informasi audio visual perihal sebuah tontonan.
Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan naskah Strategi Kebudayaan dalam rangka Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, bahwa saat ini perkembangan dunia yang semakin kompleks turut membawa budaya Indonesia bersentuhan dengan budaya negara lain. Namun di tengah kompleksitas persentuhan budaya tersebut, masyarakat harus terus menghidupkan serta menguatkan kebudayaan Indonesia. Jokowi mengatakan, bahwasanya inti kebudayaan itu adalah kegembiraan.
Cobalah rasakan apa yang terjadi selama pandemi ini. Apakah masyarakat (termasuk seniman, kalau ada) merasa gembira dengan bantuan-bantuan ekonomi itu? Apakah para seniman sudah cukup gembira bisa pentas secara daring? Apakah juga masyarakat penonton sudah merasa gembira menyaksikan pertunjukan hanya melalui layar komputer dan gawai saja? Lantas, dimanakah kegembiraan itu?

Last but not least, pergelaran kesenian memang tidak semata-mata harus dimaknai sebagai tontonan belaka. Biarkanlah peristiwa seni budaya tetap dilangsungkan dalam kemasan ritual, bukan menjadi tontonan dengan pengunjung massal. Termasuk, gelar seni budaya “Padang Bulan di Kampung Seni Sidoarjo” adalah sebuah ritual budaya. Biarkanlah seniman berkumpul dengan batasan-batasan tertentu yang tidak melanggar protokol kesehatan. Biarkanlah seniman berkreasi dengan caranya sendiri demi mencukupi kebutuhan rohani. Sesungguhnya, kelaparan rohani itu jauh lebih menyakitkan dibanding kelaparan ekonomi. (*)
- Henri Nurcahyo, Ketua Komunitas Seni Budaya BrangWetaN
(Catatan ini dibuat sebagai dasar pemikiran pergelaran “Padang Bulan di Kampung Seni” Sidoarjo yang diselenggarakan sejak tanggal 3 Oktober 2020 yang lalu, dan akan dilangsungkan lagi tanggal 31 Oktober 2020, serta bulan-bulan berikutnya).