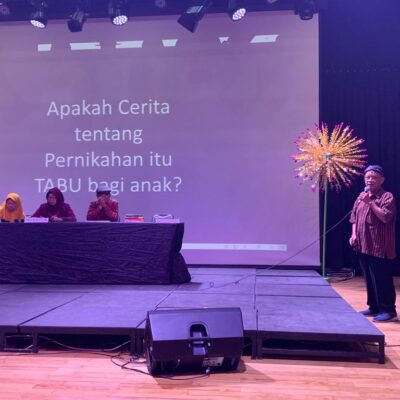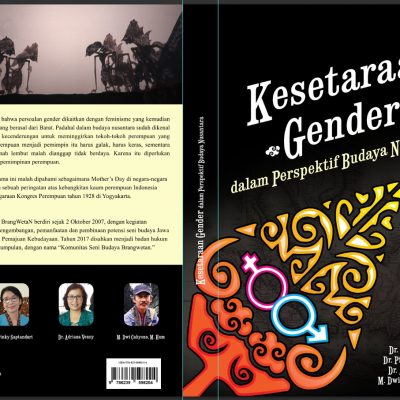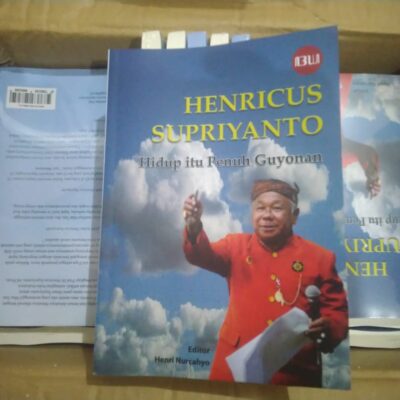Jelajah Budaya Tirtayatra (6) PEMUKIMAN BRAHMANA DI CANDI JEDONG
CANDI Jedong yang ada di Desa Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sesungguhnya bukan bangunan candi sebagaimana biasanya. Hanya ada dua buah gapura paduraksa sebagai pintu masuk sebuah areal kosong yang kira-kira seluas lapangan sepakbola. Justru areal kosong berpagar itulah sebetulnya yang “bersejarah” karena konon merupakan kompleks pemukiman para brahmana atau resi yang hidup menarik diri dari urusan dunia. Pada masa lampau, mereka berdiam di lereng gunung Penangungan, di lahan yang berundak mengikuti punggung bukit.
Sebagaimana sudah diceritakan dalam serial awal tulisan ini, perjalanan dari Candi Belahan menuju Candi Jedong melewati jalur alternatif menembus areal kawasan penambangan batu dan langsung muncul di jalan raya Japanan – Mojosari. Kami singgah di masjid besar Watukosek untuk melaksanakan sholat Jum’at. Usai ritual sholat yang hanya berlangsung setengah jam itu, perjalanan dilanjutkan masuk ke kawasan Ngoro Industrial Park namun segera berbelok ke kiri di tikungan pertama, memasuki desa Wotanmas Jedong. Dari sini lagi-lagi terlihat kawasan penambangan batu di sisi kanan jalan, hingga akhirnya sampai lokasi Candi Jedong di ujung jalan.
Pada zaman dulu, desa yang sekarang disebut Wotanmas Jedong itu bukan hanya sekadar pernah menjadi pemukiman para resi, melainkan sebuah ibukota kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Airlangga (1019 – 1042 M) yang waktu itu disebut Wwatan Mas. Ibukota kerajaan di lereng Penanggungan ini merupakan kepindahan dari Jawa bagian Tengah. Setelah itu Airlangga lantas membagi kerajaannya menjadi dua, Janggala (Kahuripan) dan Panjalu (Kadiri) yang beribukota di Daha.
Berdasarkan sumber prasasti dan sejumlah literatur, Slamet Muljana dalam buku ‘Tafsir Sejarah Negara Kretagama ‘ menguraikan kronologi ibukota kerajaan di lereng Penanggungan tersebut. Dikatakan, pada zaman pemerintahan Raja Sindok, ibukota kerajaan Sindok pada kuartal pertama abad 10 ialah Watu Galuh, kira-kira letaknya di sekitar Jombang. Pada zaman pemerintahan Dharmawangsa, sejak akhir abad 10, ibukota itu telah dipindahkan ke arah timur ke Watan di kaki gunung Penanggungan di sebelah selatan Sidoarjo, tempat dimakamkan Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa sendiri tewas sebagai korban serangan mendadak Raja Wurawari pada tahun 1006, seperti dinyatakan dalam Prasasti Pucangan, 1041.
Sampai di sini ada data menarik, bahwa selain desa Watan disebut sebagai ibukota Mataram Kuno, juga tempat dimakamkan Raja Dharmawangsa. Dimanakah posisi makam tersebut sekarang ini? Juga, apakah yang disebut Watan itu berarti desa Wotanmas Jedong sekarang ini? Perlu penelitian lebih lanjut.
Slamet Muljana menulis, setelah Airlangga (Slamet menggunakan ejaan Erlangga, hn) berhasil memusnahkan Raja Wurawari dan merebut kembali kerajaan yang didudukinya, ibukota Watan ditinggalkan karena Raja Airlangga (menurut Prasasti Cane, 1021) membangun ibukota baru di kaki gunung Penanggungan bernama Watan Mas. Sedangkan Prasasti Terep (1032) menguraikan bahwa Raja Airlangga dalam kejaran musuh lari dari Watan Mas menuju Desa Patakan. Rupanya, ibukota Watan Mas yang telah diduduki musuh itu tetap ditinggalkan karena menurut Prasasti Kamalagyan (1037) ibukota kerajaannya ialah Kahuripan di sebelah timur gunung Penanggungan. Airlangga tidak lama tinggal di situ karena pada tahun 1042 ibukotanya ialah Daha sebagaimana stempel prasasti Pamwatan dengan tulisan Dahana. Prasasti Pamwatan adalah prasasti yang terakhir yang dikeluarkan Airlangga. Tidak diketahui, apa sebab ibukotanya pindah dari Kahuripan ke Daha. (Slamet Muljana: Tafsir Sejarah Negara Kretagama. LKiS, 2011)
Dari uraian di atas disebut nama desa Watan Mas, yang ternyata berbeda dengan nama Watan yang disebut sebelumnya. Apakah keduanya mengacu pada desa Watanmas Jedong sekarang? Sejak kapan ada tambahan kata Jedong? Menurut Richadiana Kartakusuma, nama Jedong sudah disebut sekurang-kurangnya zaman Rakai Watukura Dyah Balitung, lalu Rakai Halu Pu Sindok sebagai Sanghyang Pawitra, kawasan pertapaan untuk menyatu dengan Leluhur (Pawitra). Kompleks bangunan Jedong ini disebut Sanghiyang Pawitra, yaitu leluhur yang menunjuk kepada Gunung Penanggungan itu sendiri. Gunung paling suci di Jawa Timur kaitannya dengan keagamaan pribumi yang disebut Karesian (Mandala Kadewagurwan).
Hal ini dapat diketahui dengan diketemukannya prasasti yang menyebutkan hal itu, sebagaimana dijelaskan di belakang nanti. Yang jelas, kata antropolog penyuka sejarah itu, inti dari keberadaan bangunan-bangunan ini adalah pemujaan terhadap gunung (yakni Gunung Penanggungan) maka itu bukan hanya di Jedong saja ditemukan bangunan-bangunan itu melainkan di sekeliling arah mata angin Gunung Penanggungan akan ditemukan bangunan suci yang sama. Menariknya bangunan-bangunan tersebut hampir semua tanpa atap bentuknya altar terbuka karena memang untuk pertapaan.
Yang masih belum terjawab adalah, sejak kapan nama Jedong muncul? Sebab Prasasti Tulangan (Jedong I) hanya menyebut bahwa kawasan Jedong sekarang ini justru masih disebut Tulangan, kemudian dalam prasasti berikutnya disebut Kambang Sri. Mungkin saja sebutan Jedong berasal dari masyarakat setempat. Namun tetap menarik ditelusuri toponimi kata Jedong itu sendiri. Siapa tahu dapat memberikan tambahan informasi baru.
Sekadar ilustrasi, perihal kepindahan Mataram kuna dari Jawa (di bagian) Tengah ke Jawa Timur memang menarik. Pada sekitar abad X Raja Mataram Wawa memindahkan kota kedudukan raja ke Jawa bagian timur. Sebagaimana dituturkan Agus Aris Munandar, alasan pemindahan tersebut nampaknya masih menjadi perdebatan. Hipotesis yang selama ini berkembang, ada yang menyatakan bahwa pemindahan ibukota tersebut karena wabah penyakit; ada yang bilang rakyat melarikan diri ke bagian timur karena raja-raja pada masa itu memerintah dengan kejam; hipotesis lainnya lagi menyebut perpindahan itu dipicu oleh adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya; malah ada lagi yang mengatakan bahwa alasan kepindahan itu karena bencana alam berupa letusan gunung berapi. Namun ada yang menarik, yaitu karena alasan yang menyatakan bahwa pemindahan ibukota itu sebenarnya mencari Mahameru yang lebih ideal di Jawa Timur. (Munandar, 2004, dalam “Catuspatha Arkeologi Majapahit”, 2011).
Yang kemudian menjadi menarik adalah, apapun penyebab kepindahan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu, mengapa justru memilih lereng Penanggungan? Pilihan terhadap desa Wwatan Mas (yang kemudian menjadi Wotanmas Jedong) tentu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu yang istimewa menyangkut desa ini. Dan kenyataannya sekarang, desa kuna yang sarat sejarah itu mengalami kondisi krisis air. Padahal di sinilah sumber air besar memancar pada waktu lampau.
Candi atau Situs Jedong yang sekarang ini, terletak di lereng utara Gunung Penanggungan. Tepatnya di sekitar 2 kilometer sebelah selatan Kawasan Industri Ngoro, atau sekitar 3 kilometer dari jalan utama Japanan – Mojosari. Bangunannya berada di tengah pemukiman, dengan batas-batas lingkungan sebelah utara berbatasan dengan pekarangan dan pemukiman, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan perladangan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan jalan desa.
Jadi yang disebut dengan Candi Jedong adalah dua buah gapura itu. Disyukuri saja, bahwa dengan adanya gapura ini maka Situs Jedong menjadi ada penandanya dan terpelihara dengan baik. Dari gapura itu pula dapat diketahui ada angka tahun 1385 Masehi yang menjadi penanda bahwa gapura itu dibangun pada masa Majapahit. Dan untungnya, ditemukan banyak prasasti, hingga 12 jumlahnya, yang dibuat dalam tiga zaman di lokasi ini sehingga diketahui kemudian bahwa situs Jedong sudah pernah dihuni manusia pada abad 10 atau bahkan sebelumnya.
Areal kosong itu memang tidak bisa diapa-apakan. Hanya dipagari saja, dibangun beberapa jalanan berundak untuk memudahkan penelusuran, dan ruas-ruas jalan diantara lahan tanpa bangunan yang menegaskan adanya bekas pemukiman, lengkap dengan sejumlah pepohonan besar dan kecil. Maka berdiri di ketinggian di lereng sebelah selatan, memandang hamparan lahan arah utara, bisa membayangkan rumah-rumah para resi yang entah bagaimana wujudnya. Semuanya kini sudah musnah, karena bahannya mungkin terbuat dari kayu yang tentu tidak bertahan lama. Hanya tersisa dua buah gapura sebagai pintu masuk lahan kosong itulah yang mengingatkannya.
Sebetulnya yang tersisa bukan hanya dua buah gapura, namun ada tiga gapura, sebagaimana ditulis dalam sebuah laporan tahun 1907. Dari tiga gapura itu, 2 buah diantaranya berupa gapura terbuat dari batu andesit dan satu gapura lagi terbuat dari batu bata. Gapura yang dari batu bata ini terletak sekitar 300 m di sebelah utara situs Candi Jedong, dengan poros utara-selatan, pernah diidentifikasi terpahat angka 1298 Cyaka (1376 Masehi) dan sekarang tinggal reruntuhannya saja.
Berbeda dengan dua buah gapura dari batu andesit itu, gapura yang terbuat dari batu bata ini nyaris tidak dapat dilihat stukturnya. Sekilas malah hanya seperti tumpukan batu bata biasa, sekitar dua meter tingginya, yang disusun bentuk persegi dengan areal kotak di tengahnya. Kondisinya sudah aus, hanya nampak bekas-bekas relief berupa hiasan di arah depan (utara). Sementara di ruang kosong di tengahnya disimpan beberapa artefak batu yang sudah tidak utuh lagi. Entah di bagian mana dulu artefak itu berada, dan kenapa kok batu, tidak nyambung dengan bangunan induk berupa bata. Sebagian besar bata itu memperlihatkan susunan baru yang nampaknya hanya ditata biasa saja, sementara susunan bata aslinya hanya nampak di bagian paling bawah dan sebagian di latar depan.
Kondisinya sekarang ini, tumpukan bata itu dipagari dengan kawat berduri, beserta luasan lahan di depannya. Tidak ada papan nama apapun, kecuali sebuah papan peringatan yang mengutip UU Cagar Budaya yang menandakan bahwa lokasi itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan batas-batas lahan itu juga dipatok dengan beton khusus bertuliskan “Suaka PSP”. Penduduk setempat menyebutnya Candi Pasetran. Nampaknya belum ada tanda-tanda bahwa gapura yang satu ini pernah dilakukan pemugaran.
(Bersambung)