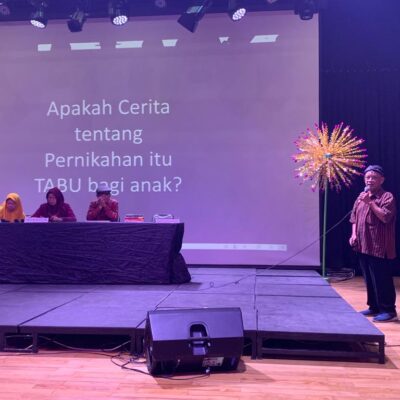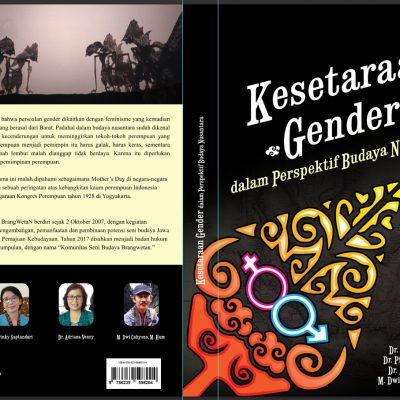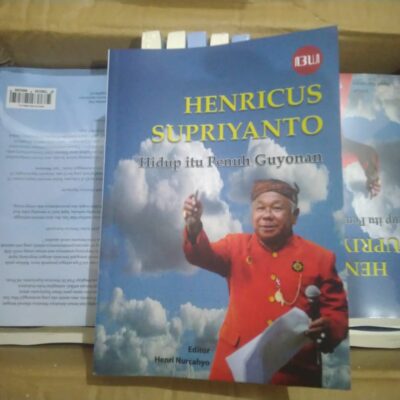Jelajah Budaya Tirtayatra (13): NAMA JALATUNDA DAN AIR AMERTA
Catatan HENRI NURCAHYO
TIDAK ada bukti yang dapat dirujuk mengenai asal mula nama Jalatunda. Yang justru berkembang adalah cerita-cerita rakyat terkait dengan Jalatunda, bahkan juga cerita mengenai perjalanan Airlangga yang didramatisasi sedemikian rupa. Dalam perspektif kearifan lokal, munculnya cerita-cerita itu mengindikasikan bahwa masyarakat setempat ingin mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan emosional-spiritual dengan Jalatunda. Bahkan ada warga setempat yang, katanya, mengaku memiliki garis keturunan langsung dengan Airlangga.
Kisah tentang pelarian Airlangga ini sesungguhnya sudah cerita menarik tersendiri, seperti bagaimana nasib istrinya, perjalanan Airlangga yang sempat singgah di wihara Budha (yang sekarang dikenal sebagai Gua Gembyang di Pacet), juga ketika Airlangga kawin (lagi) dengan puteri desa Cane (sekarang namanya Tanen, Pacet) yang tidak mampu membayar mahar sehingga Airlangga “dipaksa” tinggal di desa itu.
Bahkan dalam perjalanan kelana Airlangga (dan Narotama) itulah lahir nama Jalatunda sebagai nama mata air di kaki Gunung Bekel itu. Dalam buku “Katuturanira Maharaja Erlangga” yang ditulis Koes Indarto dalam bahasa Jawa Kawi dan bahasa Indonesia, antara lain dikisahkan bagaimana perjalanan (tepatnya pelarian) Airlangga sejak penyerangan Raja Wurawari itu. Waktu itu Airlangga ditemani Narotama mendaki gunung Penanggungan dari arah Tamiajeng, turun ke arah barat, dan menemukan sebuah mata air besar yang ditunggui oleh ular sebesar batang pohon. Ternyata ular itu kemudian menjelma menjadi Yogi, dan terjadilah dialog dengan Airlangga.
Sang Yogi banyak memberikan nasehat kepada Airlangga mengenai hidup dan kehidupan, juga perintah agar Airlangga mendirikan kerajaan, belajar segala ilmu, mengabdi pada negara, belajar berburu, berperang serta belajar menghadapi kejahatan, sebab akan ada banyak perkara di sana. Kalaupun ada perkara datang, kata Sang Yogi, lihatlah pada inti persoalannya seperti menarik jala (Jalatundha), ditarik pada pusatnya maka semua bahkan timahnya pun terangkat dan engkau mendapat ikan.
“Oleh sebab itu sejak saat ini mata air ini aku namakan Jalatundha,” kata Airlangga pada Narotama.[1]
Jika cerita itu benar adanya, maka peristiwa pemberian nama Jalatunda itu terjadi dalam kurun waktu 1006 – 1009 M. Pertanyaannya, apakah pada saat itu Candi Jalatunda memang belum ada sehingga kemudian Airlangga memberi nama sebuah mata air dengan nama Jalatunda? Padahal menurut catatan sejarah candi Jalatunda sudah dibangun tahun 997 M, jauh sebelum Airlangga menginjakkan kakinya di tanah Jawa. Atau, bisa juga patirtan itu memang sudah ada sebelumnya namun belum diberi nama, dan baru Airlangga yang kemudian memberinya nama “Jalatunda?”
Menurut Dwi Cahyono, logika nama Jalatunda seperti itu tidak masuk akal. Sebab makna kata Jala itu bukan dalam konteks bahasa Jawa sekarang yang dimaknai sebagai Jaring. Dalam bahasa Jawa Kuna, makna kata Jala adalah air, seperti dalam kata Jaladwara, yang berarti pancuran air. Tunda adalah semacam tangga atau jalan menanjak yang bertrap-trap. Jadi Jalatunda lebih masuk akal dimaknai sebagai air (mengalir dari atas) yang berundak-undak.
Penyebutan nama desa Cane bahwa Airlangga dikisahkan pernah menikah dengan anak kepala desa setempat, menurut Dwi Cahyono, kisah itu lebih bermuatan dongeng ketimbang fakta sejarah. Demikian pula kisah yang dituturkan Koes Indarto tersebut, menyebut istri Airlangga dijemput dari tempat pengasingannya di Sedayu dan berkumpul menjadi satu dengan istri muda Airlangga yang anak kepala desa itu. Dwi Cahyono yakin bahwa istri Airlangga tewas dalam penyerbuan tentara Wora-wari dalam pralaya saat pernikahan itu. Nama Cane dikait-kaitkan mungkin dihubungkan dengan temuan Prasasti Cane (943 Saka atau 1021 M), yang menjadikan sebagai Cane desa perdikan. Uniknya, prasasti bertuliskan Jawa Kuno dan terbuat dari batu ini ditemukan di daerah Surabaya.[2]
Ada juga pendapat lain, bahwa Jalatunda (Jolotundo), Airlangga, Udayana,sama-sama bermakna air berundak. Mungkinkah yang bernama itu adalah sosok yang menguasai sistem pengairan/irigasi seperti sistem subak di Bali…?
Tetapi nama Jalatunda itu sendiri tidak bisa diklaim hanya sebagai nama candi patirtan yang ada di kaki gunung Penanggungan ini saja. Di desa Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, juga terdapat umbul Jalatunda. Di kawasan budaya dan obyek wisata Dieng didapati bekas kawah yang kemudian disebut pula sumur Jalatunda. Di wilayah kecamatan Mandiraja di kabupaten Banjarnegara malah terdapat sebuah desa bernama Jalatunda, yang memiliki sumber air besar berbatasan dengan hutan desa. Jadi sebutan Jalatunda itu selalu berkaitan dengan keberadaan mata air, danau atau sumur.
Air Amrta yang Bertuah
Daya tarik utama dari Jalatunda sebagai tempat rekreasi adalah keberadaan mata airnya. Makna Jalatunda itu sendiri memang kurang lebih bersangkutan dengan sumber atau mata air (bahasa Jawa: patirtan). Tirta dalam bahasa Kawi berarti air namun juga bermakna bertapa atau pertapaan. Air suci demikian layak disebut dengan tirtha nirmala atau tirtha amerta yang dipercaya mempunyai khasiat banyak selain membersihkan dosa-dosa, menyembuhkan berbagai penyakit, juga dipandang sebagai air keabadian. Dewa-dewa dipercaya telah meminum air amerta, oleh karena itu mereka bersifat abadi tidak mengenal kematian.[3]
Karena itu patirtan bukan sekadar berarti tempat air atau kolam atau pemandian, tetapi pemandian air suci, air penghidupan, yang berfungsi untuk membersihkan atau mensucikan diri dari mala (dosa) dan untuk mencapai kelepasan (moksa). Bahkan dalam kitab Calonarang disebutkan tirta diartikan sebagai air suci untuk menghidupkan orang mati.[4]
Banyak orang yang percaya bahwa air di Jalatunda itu sarat dengan nilai spiritual. Dalam mitologi Hindu air Jalatunda ini adalah air amerta (abadi) yang bertuah. Dengan meminum atau mandi air dari jaladwara (pancuran air) itu dapat membuat orang jadi awet muda dan bisa membebaskan dirinya dari pikiran yang kacau. Tidak sedikit yang selalu membawa botol atau bahkan jerigen sebagai tempat air untuk dibawa pulang. Kebetulan di sisi kanan dan kiri bangunan itu terdapat kolam untuk mandi wanita dan laki-laki. Bagi yang tidak sempat mandi, sudah cukup puas kalau bisa membasuh muka saja dengan air pancuran dan sedikit meminumnya langsung. Masyarakat Hindu Bali hingga kini masih sering melakukan upacara untuk membersihkan diri dari dosa pada hari-hari tertentu di Patirtan Jalatunda. Bahkan ada yang membawa tirta amrta (air keabadian) ini dibawa ke Bali untuk upacara keagamaan. Setidaknya terdapat 52 pancuran air yang terdapat di candi ini.
Dari berbagai bacaan tersebut setidaknya dapat disimpulkan, bahwa makna kata Patirtan mengacu kepada tempat air yang dianggap suci, keramat atau tempat ziarah. Dan makna seperti itulah yang sekiranya tepat untuk menyebut Jalatunda.
Sementara umat Hindu yang berdomisili relatif tidak jauh dari lokasi Jalatunda (Sidoarjo dan Mojokerto), malah mengandalkan air Jalatunda untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka rela bolak-balik dengan truk ke Jalatunda membawa sejumlah gallon atau jerigen besar untuk mengambil air langsung dari pancurannya. Berbeda dengan wisatawan biasa yang hanya sekadar mengambil air begitu saja, umat Hindu melakukannya dengan proses ritual yang cermat, lengkap dengan busana serba putih, dan harus dilakukan sendiri.
Mitos awet muda terkait air Jalatunda ini bukan tanpa alasan. Sebab air yang mengalir di pancuran pada patirtan ini dipercaya sebagai amrta (air keabadian) karena berasal dari Gunung Penanggungan yang dalam kepercayaan Hindu sebagai puncak alam semesta, yakni swargaloka tempat bersemayamnya para dewa. Anggapan ini diperkuat oleh adanya peninggalan berupa arca Wisnu yang berada di bagian tengah sebagai dewa kesejahteraan manusia. Dalam konsep agama Hindu bahwa Dewa Wisnu selaku dewa pemelihara yang melangsungkan kehidupan alam semesta. (Sayang arca Wisnu itu sudah tidak di tempatnya lagi, hn).
Lepas dari mitos tersebut, keberadaan air Jalatunda ini memang dapat dirasakan lebih bagus ketimbang air kemasan yang dijual mahal dalam botol dan gelas itu. Berdasarkan penelitian, kualitas airnya terbaik di dunia dan kandungan mineralnya sangat tinggi. Meskipun klaim soal kualitas itu tidak pernah disebutkan lengkap sumbernya. Yang jelas, keunikan petirtaan ini adalah debit airnya yang tidak pernah berkurang meskipun musim kemarau.
Konon sebuah penelitian pernah dilakukan arkeolog Belanda tahun 1985, hasilnya, kualitas air di petirtan Jolotundo menduduki rangking 5 dunia. Penelitian kedua yang juga dilakukan arkeolog Belanda pada tahun 1991, kualitas air petirtan Jolotundo menduduki peringkat 3 dunia. Sayang tidak ditemukan penjelasan lebih rinci soal penelitian tersebut, apakah sudah membandingkan dengan semua mata air di seluruh dunia? Apakah hal itu mungkin dilakukan? Kabarnya pernah juga dilakukan uji coba dengan menyimpan air ini selama 2 tahun. Bau, warna, dan rasanya tak berubah.
Masyarakat desa setempat setiap tahun melakukan upacara Ruwat Sumber, pada setiap penanggalan dalam minggu pertama dalam bulan Syura. Dan ternyata, Jalatunda bukan hanya satu-satunya mata air yang memancar di desa ini melainkan masih ada puluhan mata air lain yang tersebar di pelosok desa. Seiring dengan perkembangan pengelolaan lahan oleh penduduk, sebagian mata air itu sudah tidak memancarkan air lagi. Bahkan sebuah penelitian dari mahasiswa Universitas Airlangga, kualitas air Jalatunda sendiri sudah tidak seperti dulu.
Satu hal yang menarik, sebagaimana dituturkan Gatot Hartoyo, keberadaan pancuran air dari bangunan yang berundak itu sesungguhnya merupakan sebuah orkestra tersendiri. Bayangkan, puluhan pancuran air secara bersama-sama mengalir dalam debit yang berbeda di kolam yang juga berbeda. Kalau mau menikmati dalam suasana hening, di tengah malam misalnya, akan terdengar sebuah simponi air yang indah. Hanya mendengarkan bunyi satu pancuran saja sudah mendatangkan ketenangan batin sebagaimana yang disukai orang Jepang. Bagaimana kalau puluhan pancuran sebagaimana yang ada di patirtan Jalatunda ini. Meskipun, sangat mungkin model pengaturan pancuran yang seperti itu memiliki landasan filosofis tersendiri.[5] (*)
(Bersambung)
[1] Koes Indarto. Katuturanira Maharaja Erlangga. Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan. Lembaga Javanologi Surabaya, Koordinator Jawa Timur, 2008.
[2] Ninie Susanti, Biografi Airlangga
[3] Agus Aris Munandar. Departemen Arkeologi FIB UI. “Patirtan di Pawitra: Jalatunda dan Belahan. Majalah Arkeologi Indonesia. Diunduh dari http://hurahura.wordpress.com/2011/01/01/patirthan-di-pawitra-jalatunda-dan-belahan/
[4] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Opcit
[5] Gatot Hartoyo, pemerhati budaya desa Seloliman, Trawas, Mojokerto. Wawancara pribadi.